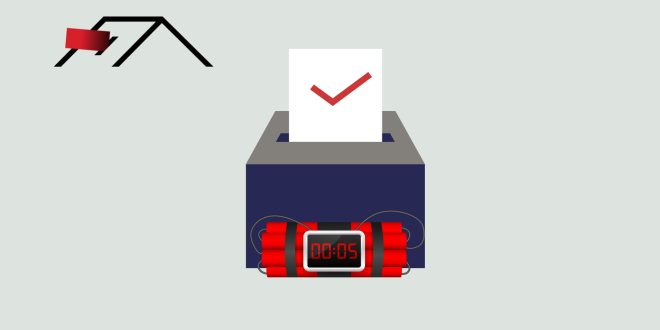Varieties of Democracy (V-Dem) melalui “Democracy Report 2023” melaporkan, sebanyak 43% dari jumlah populasi dunia saat ini hidup di negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi, di antaranya Indonesia. Dasar kemunduran tersebut adalah menurunnya kebebasan berekspresi, meningkatnya sensor pemerintah terhadap media, represifitas terhadap masyarakat sipil, dan memburuknya kualitas pemilu.
“Dulu indeks demokrasi Indonesia ditopang oleh pemilu, khususnya dari aspek penyelenggara pemilu dan proses penyelenggaraannya. Kedua hal tersebut biasanya yang menutupi kemunduran demokrasi di Indonesia. Sehingga yang harusnya warna demokrasi kita merah, melalui tata kelola pemilu itu warnanya menjadi kuning gitu,” kata Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menjelaskan Indeks Demokrasi Elektoral (IDE) di Gedung Auditorium Juwono Sudarsono, UI, Depok, Jawa Barat (5/12).
Dari instrumen demokrasi elektoral, skor IDE Indonesia menunjukkan penurunan hingga 16% dalam 10 tahun terakhir. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2021, yang mengalami penurunan skor hingga 4,4% dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan indikatornya, dalam 10 tahun terakhir pemilu bersih mengalami penurunan skor indeks paling tinggi hingga 14,1%.
Titi menilai, pemilu yang sebelumnya menjadi penetralisir demokrasi Indonesia dalam pengukuran global sedang mengalami ancaman yang serius. Karena sepanjang pemilu 2024 sudah terjadi banyak kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, mulai dari pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemilu hingga afirmasi keterwakilan perempuan di legislatif.
“Janji manis soal pemilu 2024 secara prosedural akan lebih baik dan stabil karena UU Pemilu tidak berubah. Harusnya praktik baik di pemilu 2019 itu tidak diotak-atik, karena yang dijanjikan adalah stabilitas, namun nyatanya yang terjadi tidak demikian,” ujarnya.
Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini lebih melayani Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibandingkan masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya keterlibatan partai politik yang ada di DPR dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam pemilu. Padahal menurut Titi, jika penyelenggara pemilunya berintegritas, setengah keinginan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas sudah terwujud.
“Sebab kalau aturan mainnya kurang baik, namun penyelenggaranya berintegritas, dengan inovasi, terobosan, dan komitmen demokrasi bisa menghasilkan aturan yang lebih adaptif. Tapi kalau tidak punya integritas, aturan yang baik pun sama saja, tidak punya makna,” imbuhnya.
Selain itu Titi juga menyoroti Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang terlalu kompromi dengan peserta pemilu dalam hal kampanye. Harusnya di tengah kemajuan teknologi dan berkembangnya kreativitas kampanye, Bawaslu memberi batas yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye.
“Karena pembiaran terlalu lenturnya aktivitas politik di masa kampanye membuat dana-dana illegal tidak bisa kita tagih akuntabilitasnya, dan hal itu sangat berbahaya sekali,” tutup Titi.
Sementara itu Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menjelaskan, praktik otokratisme di Indonesia gampang diterima karena hukum yang seharusnya membuka akses yang sama untuk semua orang tidak terjadi di Indonesia. Hal itu terjadi karena demokrasi dengan sengaja telah dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu.
Bivitri menyebut setidaknya terdapat empat institusi yang dilemahkan untuk membunuh demokrasi. Di antaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK, DPR dimatikan melalui fungsi pengawasan, karena 82% anggota DPR periode 2019-2024 berasal dari koalisi pemerintah. Kemudian pembatasan kebebasan masyarakat sipil melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pergantian hakim Aswanto karena dianggap terlalu sering membatalkan keputusan-keputusan DPR.
“Alhamdulillah hari ini nggak jadi diketok perubahan UU MK untuk menyingkirkan hakim yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah dan DPR,” kata Bivitri.
Menurutnya cara pembajakan demokrasi melalui konstitusi juga marak terjadi di negara lain, seperti Hungaria dan Venezuela. Kedua negara itu juga menggunakan pola yang sama, yakni melalui mematikan institusi yang seharusnya mengawasi kekuasaan dan pembajakan demokrasi melalui konstitusi. Fenomena itu terjadi karena dalam hukum segalanya bisa disembunyikan.
“Karena di balik pasal peraturan semua jadi bersembunyi. Hukum bisa dijadikan alat sembunyi dari penyelewengan-penyelewengan kekuasaan,” tegasnya.
Menurut laporan Freedom House, Indonesia memiliki skor yang rendah dalam budaya politik dan kebebasan sipil. Status Indonesia sejak tahun 2015 hingga saat ini belum mampu beranjak dari setengah bebas (partly free), bahkan kian merosot dari tahun ke tahun.
Dua aspek tersebut yang juga dianggap Direktur Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah sebagai hal yang sangat signifikan menghambat perbaikan mutu demokrasi kita. Pengikisan demokrasi di Indonesia menurutnya sudah terjadi dalam waktu yang panjang, karena orang-orang yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru menjadi aktor yang paling tidak demokratis.
“Hal itu terjadi ketika demokrasi menjadi alat yang digunakan oleh orang-orang yang tidak punya perspektif demokrasi dan tidak menjadikan demokrasi sebagai tujuan,” tuturnya.
Untuk itu, menurutnya kehadiran oposisi dan perjuangan masyarakat sipil harus punya nafas yang panjang untuk menjaga demokrasi. Karena menurutnya, pelemahan terhadap demokrasi melewati tiga cara, yakni; stigmatisasi pada kritik oposisi, kriminalisasi, dan melalui cara legal, prosedural, dan formal.
“Jadi cara kita menjaga demokrasi yakni memperkuat masyarakat sipil dan menciptakan ruang-ruang baru. Misalnya pakai sosial media atau melalui legal formal, yang intinya kita menyamakan arena permainan,” imbuh Hurriyah.
Selain itu dalam konteks pemilu, ia juga menganggap penting untuk melibatkan anak muda dalam proses pengawalan pemilu. Menurutnya Gen Z adalah generasi yang biasa berfikir kritis dan biasa membedakan informasi yang benar dan salah. Yang menjadi masalah menurutnya, informasi mengenai pemilu tidak cukup tersedia, yang akhirnya tidak mampu menyentuh anak muda.
“Maka mari isi diskursus politik kita dengan memanfaatkan beragam sosial media untuk memberikan informasi pada anak muda. Dan biarkan mereka yang memilih nantinya,” tutupnya. []
AJID FUAD MUZAKI
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal