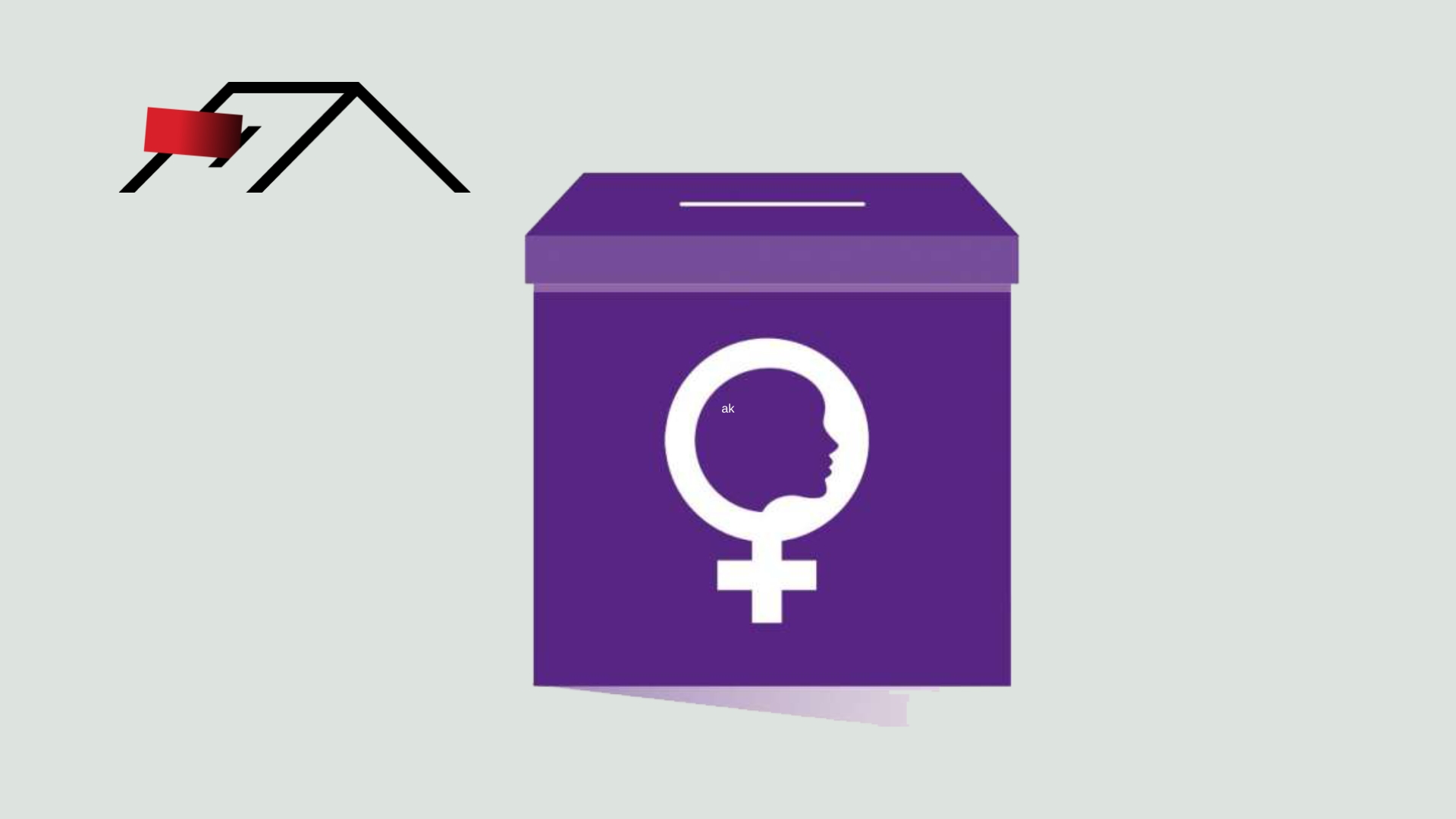Di tepi Taman Tunas Bangsa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), tepat di depan Gedung F, Auditorium Juwono Sudarsono, Stevi duduk pada salah satu bangku beratap hijau yang disebut “kubikel” oleh mahasiswa FISIP UI. Saat ditemui oleh Suara Mahasiswa UI pada Kamis siang (15/01), mahasiswi jurusan ilmu politik angkatan 20 itu segera menyapa dengan senyum hangat. Hari itu, Stevi menceritakan dengan jujur bagaimana ia memutuskan untuk memasuki dunia politik dengan tekad yang kuat, walaupun sebelumnya ia sempat merasa ragu.
Dalam perjalanannya, ia pernah merasakan dilema yang sama. Tepatnya ketika ia harus memilih jurusan ilmu politik sebagai jalur pendidikannya untuk terjun ke dunia politik sebagai rencana karirnya.
“Jujur, sebelum gua memutuskan untuk ikut politik praktis, gua mempunyai ketakutan yang cukup besar,” ujar Stevi memulai ceritanya.
Ia menekankan akar dilema utamanya bahwa politisi perempuan seringkali menjadi objek seksualitas, baik penampilannya hingga posisinya. Misalnya, beberapa politisi laki-laki bahkan sengaja mencari pasangan yang menarik secara fisik untuk mendulang suara, sehingga dalam hal ini perempuan digunakan sebagai “get voters” oleh calon politisi menjelang pemilu.
“Jelas sulit sekali untuk mengubah budaya patriarki di dunia politik. Boro-boro di organisasi politik, terkadang di kelas kuliah aja, kita bisa melihat bahwa lebih banyak laki-laki yang bertanya. Di sini terlihat bahwa tradisi bersuara itu lebih dimiliki laki-laki, sehingga mungkin banyak perempuan udah minder duluan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Tokenisme ini tidak hanya berlaku pada pilihan istri pejabat. Meski Indonesia sudah memiliki aturan resmi keterwakilan politik perempuan, ia menyaksikan bagaimana di lapangan perempuan yang dicalonkan nyatanya seringkali dijadikan sekedar token untuk memenuhi syarat kuota.
“Seringkali partai politik masukin perempuan ke politik hanya untuk memenuhi syarat administratif. Perempuan-perempuan ini kadang hanya dimajuin di dapil-dapil yang bukan basis partai, jadi mereka maju hanya dijadikan suicide mission aja, udah pasti nggak kepilih,” terang Stevi.
Stevi memberikan contoh, “Misalnya partai A kuat di Jawa Barat, tapi lemah di Jawa Tengah. Dia dicalonkan di Jawa Tengah. Yang penting kan partainya mencalonkan 30% perempuan, masalah dia menang atau engga, dia dicalonkan di dapil mana, itu jadi kewenangan ketua partainya lagi kan?”
Alhasil Stevi menyimpulan, hal ini menggambarkan bahwa partai-partai politik di Indonesia belum memiliki komitmen dalam mengkaderisasi anggota perempuannya dengan baik. Apalagi jika perempuan tersebut masih muda, dia sering mendengar aturan tidak tertulis mengenai ‘senioritas’ dalam pencalonan.
“Bahkan jika perempuan tersebut, penokohannya sudah oke, dia udah dikenal di dapilnya, tapi ngga dimajuin karena dia masih muda dan ngga senior, karena partai lebih prioritasin yang senior dulu, biar ngga ‘ngelangkahin senior-seniornya’,” jelas Stevi.
Perempuan yang berminat berkarir di dunia politik seperti Stevi mungkin tidak hanya akan mendapat tantangan dari eksternal, tapi juga internal. Misalnya, sebagai perempuan keluarganya seringkali bimbang mengenai pilihan karir Stevi. Kekhawatiran ini terkait dengan gender perempuan yang identik dengan peran domestik, yang seolah harus lebih memilih mengurus rumah tangga ketimbang mengejar karirnya.
Bukan Masalah Indonesia Saja
Keresahan Stevi sebagai perempuan muda yang berminat berkarir di dunia politik tentu sangat beralasan. Selama berabad-abad, budaya patriarki mengunci akses perempuan ke ranah publik, khususnya dalam posisi-posisi strategis seperti politik. Berbagai riset sosial menunjukkan pentingnya partisipasi politik perempuan pada isu-isu penting seperti perubahan iklim, keadilan rasial, kesetaraan gender, serta pembangunan berkelanjutan. Perempuan merupakan pendukung kuat kebijakan kolaborasi dan akuntabilitas antar generasi menuju dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan setara. Sayangnya, hingga saat ini data menunjukkan bahwa suara perempuan masih kurang terwakili di setiap tingkat pengambilan keputusan di seluruh dunia.
Data UN Women per 1 Januari 2023 menunjukkan dari 195 negara di dunia, hanya 17 negara yang memiliki Kepala Negara perempuan, hanya 19 negara yang memiliki Kepala Pemerintahan perempuan, dan hanya 14 negara yang mencapai 50% atau lebih jumlah perempuan dalam kabinet. Dengan kata lain, sekitar 90% posisi pengambilan kebijakan tertinggi di negara-negara di dunia didominasi laki-laki. Dengan kondisi ini, kesetaraan gender di dunia politik mungkin baru dapat tercapai 130 tahun lagi.
Kendati berjalan dengan sangat lambat, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen nasional secara global mengalami peningkatan secara bertahap dari 15 persen pada 2002 menjadi 19,8 persen pada 2012. Pertanyaannya, mengapa angka partisipasi perempuan di dunia politik berjalan lambat?
Sejarah mencatat betapa sulitnya perempuan mendapatkan hak pilih (voting rights). Pemilu pertama di dunia diselenggarakan di Athena, Yunani pada 508-507 SM. Saat itu, perempuan dikecualikan dari pemilihan umum karena masyarakat menganggap otak perempuan tidak memiliki nalar yang sempurna untuk menentukan pilihan politik. Bahkan di negara yang dianggap paling demokratis sekalipun, di Amerika Serikat, perempuan baru mendapatkan hak pilihnya setelah 144 tahun Amerika merdeka.
Hingga pada 1952, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Politik Perempuan menetapkan bahwa “perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi apa pun.” Oleh karena itu, tidak heran mengapa hingga saat ini partisipasi politik perempuan masih minim. Jangankan mencalonkan diri, untuk mendapatkan hak memilih saja, perlu lebih dari seratus tahun perjuangan.
Di Indonesia sendiri, hak pilih perempuan sudah diberikan sejak pemilu pertama tahun 1955. Hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan Indonesia pada pemilihan umum 2019 lebih banyak dari laki-laki. Dari total 187 juta pemilih, ada 92,9 juta pemilih perempuan.
Namun, jumlah pemilih perempuan yang banyak ini tidak diimbangi dengan jumlah perwakilan politik yang proporsional. Upaya untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah didorong sejak 2003 dengan lahirnya berbagai aturan hukum yang mendorong kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam organisasi sosial politik dan badan perumusan kebijakan, mulai dari menjamin persamaan hak memilih dan dipilih hingga menempati posisi jabatan birokrasi.
Selain aturan pemberlakukan kuota pencalonan perempuan minimal 30% pada setiap partai politik, diterapkan pula“zipper system”. Ketentuan ini mengatur agar dalam setiap tiga bakal calon di badan legislatif atau eksekutif, ada sekurangnya satu orang perempuan yang mendapatkan nomor urut jadi, yaitu pada tiga nomor urut pertama, tidak di bawah nomor urut tersebut. Kendati demikian, aturan-aturan ini belum dapat menjadi jaminan keterwakilan politik perempuan.
Tidak Cukup dengan Afirmasi
Hal ini dikonfirmasi Dosen Filsafat UI sekaligus akademisi feminis Jurnal Perempuan, Ikhaputri Widiantini. Perempuan yang biasa disapa Upi ini mengatakan, berbagai aturan hukum yang dibuat itu belum tentu akan menambah jumlah perempuan atau menambah jumlah kebijakan pro-perempuan.
“Indonesia memang memiliki berbagai kebijakan afirmasi seperti kuota 30% untuk perempuan, tapi kadang-kadang orang-orang merasa cukup dengan kebijakan afirmasi saja. Padahal kenyataannya, banyak partai-partai mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif. Jadinya tokenisme, yang penting ada perempuannya,” ujar Upi pada (15/03).
“Oke, ada partisipasi, tapi apakah opini atau suara perempuan di dalamnya dipertimbangkan?” tanya Upi.
Politikus perempuan Indonesia, Tsamara Amany melontarkan hal senada. Ketua DPP PSI selama 2017-2022 ini melihat sistem dan kultur partai di Indonesia masih sangat maskulin. Ajakan untuk masuk ke dunia politik terhadap perempuan tampak sebatas basa-basi saja.
“Eh, ada saudara perempuan, ngga? suruh nyaleg,” ujar Tsamara menirukan kaderisasi dan pencalonan perempuan dalam partai politik. Hal ini seringkali hanya untuk memenuhi kuota afirmasi pada Rabu (15/1).
Perempuan melibatkan diri dalam politik dengan modal yang minim. Keadaan ini jadi sebab, hanya sedikit perempuan yang bisa menang masuk parlemen atau kepala daerah.
“Akhirnya cuma sedikit dari perempuan-perempuan ini yang punya kemampuan bertarung melawan politisi-politisi yang lebih handal dan senior,” tambah Tsamara.
Mengekor ironi tersebut, Tsamara menegaskan bahwa belum banyak partai yang berinisiatif dalam melakukan pemberdayaan serius terhadap anggota-anggota perempuannya. Secara umum seperti itu, apalagi terhadap perempuan.
“Kaderisasi belum serius. Harus kita akui ini,” terang Tsamara. []
DIAN AMALIA ARIANI
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2019
Pemimpin Redaksi Badan Otonom Suara Mahasiswa UI
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal