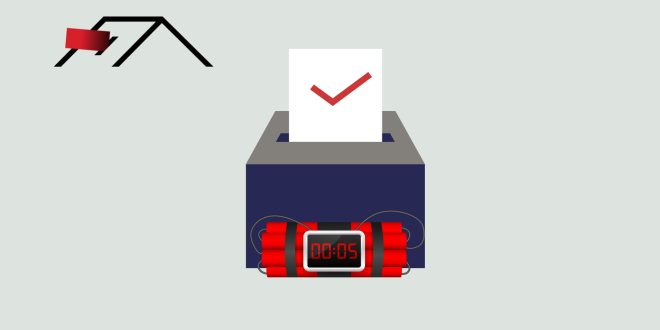Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak pada Pemilu 2024 berpotensi menjadi alasan pembenaran pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpihak pada kandidat tertentu. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis khawatir penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik semakin marak dilakukan, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi.
“Pernyataan itu dapat merusak integritas dan netralitas proses demokratis yang seharusnya melibatkan partisipasi yang setara dan adil dari semua pihak,” kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam diskusi bertajuk “Pemilu Curang: Menyoal Netralitas Presiden hingga Laporan Kemhan ke Bawaslu”, di Jakarta (25/1).
Julius menilai pernyataan Presiden Jokowi seharusnya dimaknai sebagai penyalahgunaan kekuasaan, karena terdapat indikasi mengintervensi lembaga-lembaga di luar eksekutif. Menurutnya upaya Presiden Jokowi untuk memenangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka terlihat jelas melalui dari kasus kecurangan pemilu yang melibatkan pejabat dan aparat negara dari berbagai tingkatan.
“Sebelum pemilu kita hancur dan kemudian tidak legitimatif, presiden harus cuti. Kalau dia tidak cuti maka ini sudah bukan pelanggaran etik dan pelanggaran administrasi lagi, namun sudah masuk kategori pidana,” kata Julius.
Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, berdasarkan pemantauan Imparsial, sebelum masuk masa kampanye setidaknya terdapat 64 kasus ketidaknetralan dan kecurangan yang melibatkan pejabat dan aparatur negara di berbagai tingkat dan jabatan serta aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Menurutnya mayoritas kasus ketidaknetralan dan kecurangan pemilu yang ditemukan oleh organisasi tersebut jelas menguntungkan pasangan pasangan Prabowo-Gibran.
“Salah satu pola yang kita temukan adalah penggunaan fasilitas negara, mulai dari anggaran termasuk juga penggunaan pengaruh sebagai pejabat politik dan pejabat publik di level pemerintah,” jelasnya.
Menjelang hari pemilihan Gufron menyatakan terjadi peningkatan tren kecurangan dalam pemilu, hal itu menurutnya mencerminkan rendahnya kesadaran pejabat dan aparatur negara untuk menaati aturan main dalam pemilu. Namun untungnya dengan literasi digital masyarakat yang semakin baik, kasus-kasus kecurangan tersebut dapat terungkap.
“Tindakan penyimpangan dan kecurangan yang melibatkan pejabat dari berbagai level menunjukkan bahwa praktik ini terjadi secara masif dan semakin vulgar,” imbuhnya.
Koalisi masyarakat sipil juga mendesak agar lembaga-lembaga pengawas, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga integritas pemilu. Untuk menghadapi kondisi ini Gufron mengingatkan pentingnya respons bersama dari masyarakat sipil dan penyelenggara pemilu untuk melawan praktek-praktek yang mengancam masa depan demokrasi.
“Temuan-temuan ini menjadi panggilan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur Gufron.
Mengenai dinamika politik dan hukum yang terjadi dalam proses pemilu, akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivitri Susanti mengatakan, pentingnya untuk selalu melakukan pengecekan kekuasaan dan transparansi penyelenggaraan kekuasaan. Tanpa hal itu kekuasaan akan kental dengan nuansa otoritarianisme yang dilindungi oleh kerangka hukum. Hal itu tergambar dalam kompleksitas UU Pemilu belum sepenuhnya dirancang untuk menanggapi isu nepotisme yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Jadi kita berantemnya lelah, karena yang akan digunakan justru hukum, karena hukumnya memang berpihaknya kepada orang-orang yang sebenarnya otokrat itu,” jelas Bivitri.
Menurut Bivitri jika mengacu Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, presiden memang berhak untuk berpolitik namun presiden tidak boleh melakukan kampanye selama masih menjabat sebagai kepala negara. Menurutnya ketentuan itu pada intinya memberi kesempatan kepada presiden sebagai petahana yang maju dalam pemilu untuk periode kedua. Misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika maju lagi dalam Pilpres 2009 dan Presiden Jokowi saat berkontestasi pada periode kedua.
“Politik hukum undang-undang ini sebenarnya ada dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilu itu asasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi ada konteks keadilan pemilu yang ingin dijaga oleh undang-undang,” terangnya.
Lebih lanjut, sikap presiden yang menyatakan pejabat publik boleh berkampanye juga melanggar aturan dalam UU Pemilu. Menurutnya pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi membuka ruang pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ia melihat kemungkinan tersebut sebagai respons terhadap pelanggaran undang-undang yang dilakukan presiden, meskipun ia juga mengakui rumitnya proses pemakzulan. Namun ia melihat proses itu sebagai upaya mendasar untuk menjaga demokrasi dan memeriksa kekuasaan eksekutif oleh lembaga legislatif.
“Secara prosedur ya memang rumit banget sih. Harus dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dulu setuju, DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK), terus ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di MPR harus quorum 2/3, dan yang setuju harus 2/3 dari yang hadir,” jelasnya.
Bivitri menekankan, pemilu bukanlah acara meriah semata melainkan sebuah perjuangan untuk demokrasi. Untuk itu ia berharap peran penting masyarakat sipil dalam mendukung demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. []
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal