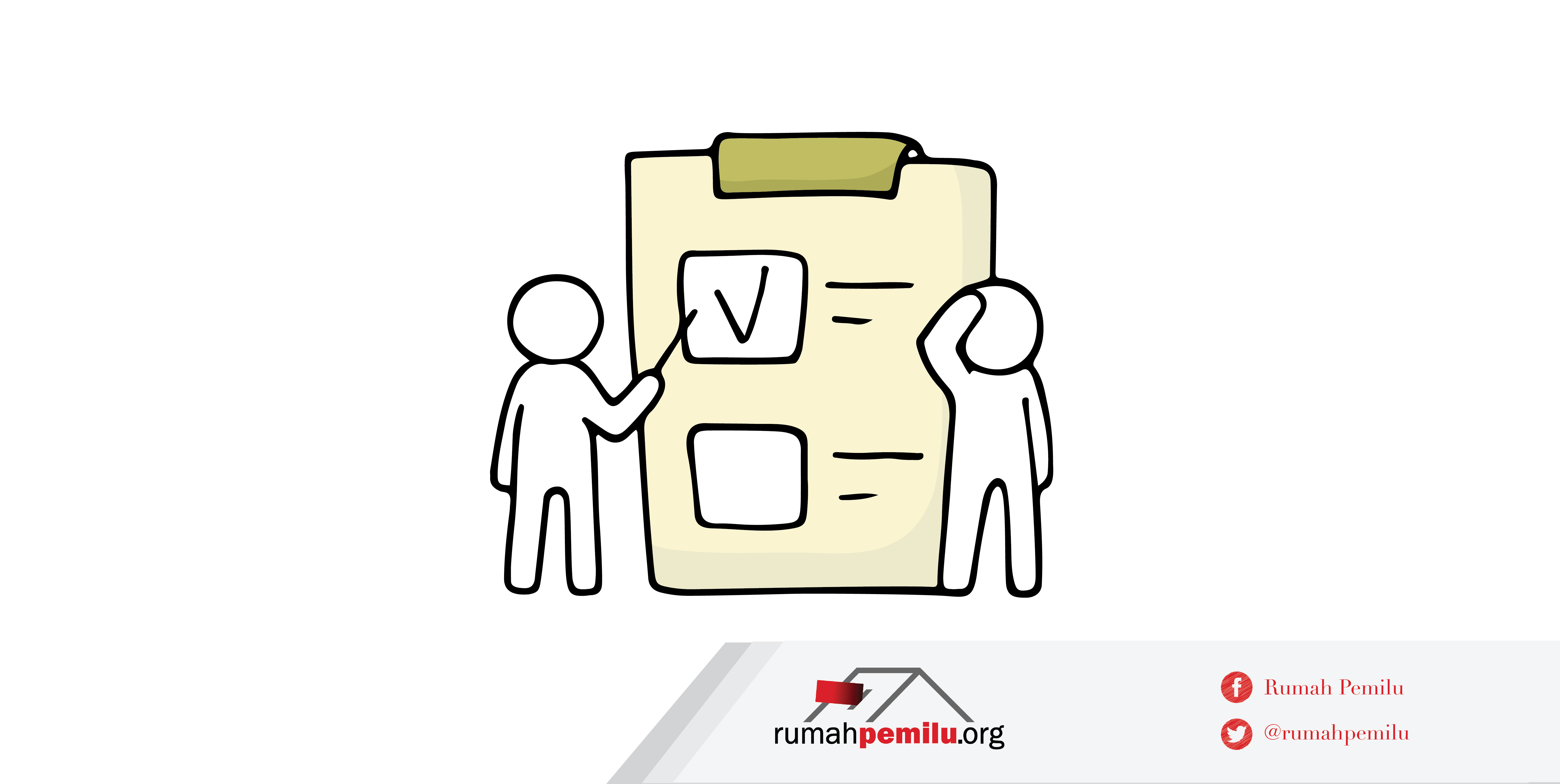Di luar kegembiraan kolektif kita atas pilkada serentak 2018 yang berlangsung relatif aman dan damai, tak kurang dari 16 pasangan calon (paslon) harus bersaing melawan kotak kosong.
Di Kota Makassar, kotak kosong diduga menang atas paslon tunggal. Mengapa fenomena pilkada kotak kosong meningkat? Apa dampaknya bagi demokrasi kita? Pilkada kotak kosong bukanlah fenomena unik pilkada serentak 2018. Pada pilkada serentak 2015 dan 2017, kehadiran kotak kosong sebagai ”pesaing” paslon sudah muncul. Hanya, jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan paslon tunggal meningkat pesat pada 2018 menjadi 16 daerah kabupaten dan kota.
Padahal, pada 2015 hanya ada tiga daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan paslon tunggal, yang kemudian meningkat menjadi sembilan daerah pada pilkada serentak 2017. Selain jumlah daerah yang meningkat cukup drastis, penyebaran daerah penyelenggara pilkada kotak kosong juga semakin meluas, mencakup tiga daerah di Sumatera, satu daerah di Kalimantan, lima daerah di Sulawesi, tiga daerah di Papua, dan bahkan empat daerah di Jawa.
Mengapa kotak kosong?
Mengapa fenomena pilkada kotak kosong muncul dan bahkan kian meningkat pada 2018. Paling kurang ada tiga faktor yang menyebabkan hal itu. Pertama, regulasi pilkada dalam bentuk UU Pilkada No 10 Tahun 2016 terlampau berat mengatur syarat pengajuan paslon, baik bagi parpol dan gabungan parpol, maupun bagi kandidat perseorangan. Untuk mengajukan paslon, parpol dan/atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD setempat.
Mengingat perolehan suara parpol dalam pemilu legislatif di daerah sangat fragmentatif, tidak mudah bagi parpol mengajukan paslon secara sendiri tanpa berkoalisi dengan parpol lain.
Sementara itu, bagi calon perseorangan, mereka yang berminat bersaing dalam pilkada harus memenuhi persentase syarat dukungan yang sangat berat, yakni 6,5 hingga 10 persen dari jumlah penduduk.
Untuk pilkada gubernur di wilayah dengan jumlah penduduk dua juta jiwa atau kurang, paslon perseorangan diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya 10 persen dukungan dari jumlah penduduk—dibuktikan dengan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk—yang kelak diverifikasi oleh KPU.
Syarat dukungan di provinsi besar dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa atau lebih memang hanya 6,5 persen, tetapi dengan nominal jumlah KTP yang harus dikumpulkan jauh lebih besar lagi. Pola serupa berlaku untuk pilkada kabupaten dan kota.
Kedua, tingginya ”biaya perahu” atau mahar politik yang harus disetor paslon kepada parpol agar bisa diusung dalam pilkada. Mantan Ketua Umum PSSI La Nyala Mattalitti pernah mengeluh di depan publik karena dimintai mahar puluhan miliar rupiah agar bisa diusung oleh Partai Gerindra dalam Pilgub Jawa Timur.
Salah seorang kandidat dalam Pilgub Sulawesi Selatan 2018, pernah diminta menyetor Rp 45 miliar oleh seorang menteri agar bisa diusung oleh suatu parpol. Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang maju dalam Pilgub Jawa Barat mengaku diminta mahar Rp 10 miliar oleh oknum partainya sendiri, padahal Dedi yang akhirnya berpasangan dengan Deddy Mizwar bukan hanya kader ”Partai Beringin”, tetapi juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat.
Meskipun jajaran parpol membantahnya, termasuk bantahan Gerindra bagi La Nyala dan bantahan Golkar terhadap Dedi, dalam realitasnya praktik keharusan setor mahar politik ini membuat para tokoh terbaik daerah enggan maju bersaing dalam pilkada.
Ketiga, gagal dan mandeknya kaderisasi parpol. Pada umumnya parpol di negeri ini bukan hanya tidak menjadikan kaderisasi sebagai basis perekrutan politik, melainkan juga kaderisasinya sendiri tidak berjalan. Akibatnya, sebagian partai lebih memilih jalan pintas dan pragmatis, yakni menunggu permohonan rekomendasi dari figur publik yang ingin maju dalam pilkada.
Parpol tidak bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya sehingga para elite parpol akhirnya hanya ”memperjualbelikan” otoritas sebagai pemberi rekomendasi bagi setiap paslon yang hendak berkompetisi dalam pilkada. Ini tentu sebuah ironi di tengah begitu tingginya ekspektasi publik atas peningkatan kualitas demokrasi kita.
Kandidasi oligarkis
Tiga faktor di balik meningkatnya fenomena kotak kosong di atas pada gilirannya berdampak pada dua kecenderungan. Pertama, terbatasnya peluang bagi tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten, tetapi tak berpartai dan tak memiliki modal finansial untuk menyetor mahar politik sehingga proses pencalonan dalam pilkada akhirnya berlangsung secara oligarkis.
Jangankan anggota dan kader parpol, tak jarang para pengurus parpol pun benar-benar tak tahu, mengapa seseorang dipilih untuk diusung sebagai paslon, dan mengapa seseorang yang lain ditolak. Proses kandidasi hanya diketahui oleh segelintir elite parpol secara terbatas, yakni mereka yang cukup dekat dengan ketua umum dan/atau tokoh sentral parpol.
Kedua, terbukanya peluang bagi siapa pun yang memiliki modal finansial serta menguasai sumber daya sosial, ekonomi dan politik yang memadai untuk “memborong” dukungan parpol, sehingga kian memperkecil munculnya pesaing dalam pilkada. Sangat mungkin sebagian pilkada kotak kosong pada 2018 dilatarbelakangi oleh kecenderungan ini, sehingga paslon tunggal berharap bisa memenangkan pertarungan dengan mudah. Dalam Pilkada Serentak 2015 dan 2017, pilkada dengan paslon tunggal pada umumnya menang secara mutlak melawan kotak kosong.
Masa Depan Demokrasi
Secara teori, kompetisi demokratis yang sehat melalui pemilu dan pilkada meniscayakan hadirnya lebih dari satu kandidat yang bersaing. Itu artinya, semakin banyak jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan paslon tunggal, merefleksikan ada sesuatu yang salah dalam proses kompetisi demokratis pilkada. Betapa tidak, paling kurang ada 10 parpol yang memiliki kursi di legislatif daerah, tetapi tidak ada persaingan politik. Pertanyaannya, mengapa harus ada 10 parpol jika mereka memiliki visi dan haluan politik yang seragam dalam bentuk pengusungan paslon tunggal dalam pilkada?
Di samping itu, jika pilkada dengan paslon tunggal dimenangi kotak kosong, pemerintah harus mengedrop pejabat kepala daerah sebelum pilkada ulang dilakukan pada gelombang pilkada serentak berikutnya. Karena itu, tidak terbayangkan jika pada pilkada serentak gelombang keempat (2020) muncul lebih banyak daerah dengan paslon tunggal yang dimenangi oleh kotak kosong sehingga pemerintah harus menyuplai pejabat kepala daerah selama jangka waktu yang cukup lama, yakni hingga pilkada serentak periode berikutnya pada 2024.
Dalam situasi demikian, kepentingan dan hak publik dikorbankan, padahal tujuan akhir dari sistem demokrasi adalah mewadahi dan memenuhi aspirasi publik itu sendiri.
Oleh karena itu, pemerintah dan partai-partai di DPR sebagai pembentuk UU perlu memikirkan ulang berbagai pengaturan pencalonan pilkada yang tak hanya membatasi peluang munculnya calon-calon pemimpin terbaik di daerah, tetapi justru lebih memfasilitasi dominasi oligarki dalam proses kandidasi pilkada.
Di sisi lain, sudah saatnya negara mewajibkan parpol kita menjadikan kaderisasi sebagai basis perekrutan politik agar parpol tidak sekadar memperjualbelikan surat rekomendasi bagi paslon dalam pilkada, tetapi juga benar-benar menjadi institusi demokrasi yang melahirkan para pemimpin politik di tingkat nasional dan daerah.
Itu artinya, selain keniscayaan revisi UU Pilkada, perlu revisi UU Parpol, agar fenomena pilkada kotak kosong tak mencederai demokrasi ke depan. Selain itu, revisi UU Parpol perlu agar kepemilikan parpol oleh sejumlah individu secara oligarkis diakhiri, sehingga kedaulatan parpol bisa dikembalikan kepada mereka yang berhak, yakni para anggotanya.
SYAMSUDDIN HARIS, GURU BESAR RISET LIPI
Dikliping dari artikel yang terbit di harian Kompas edisi 3 Juli 2018 di halaman 6 dengan judul “Demokrasi Kotak Kosong”. https://kompas.id/baca/opini/2018/07/03/demokrasi-kotak-kosong/
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal