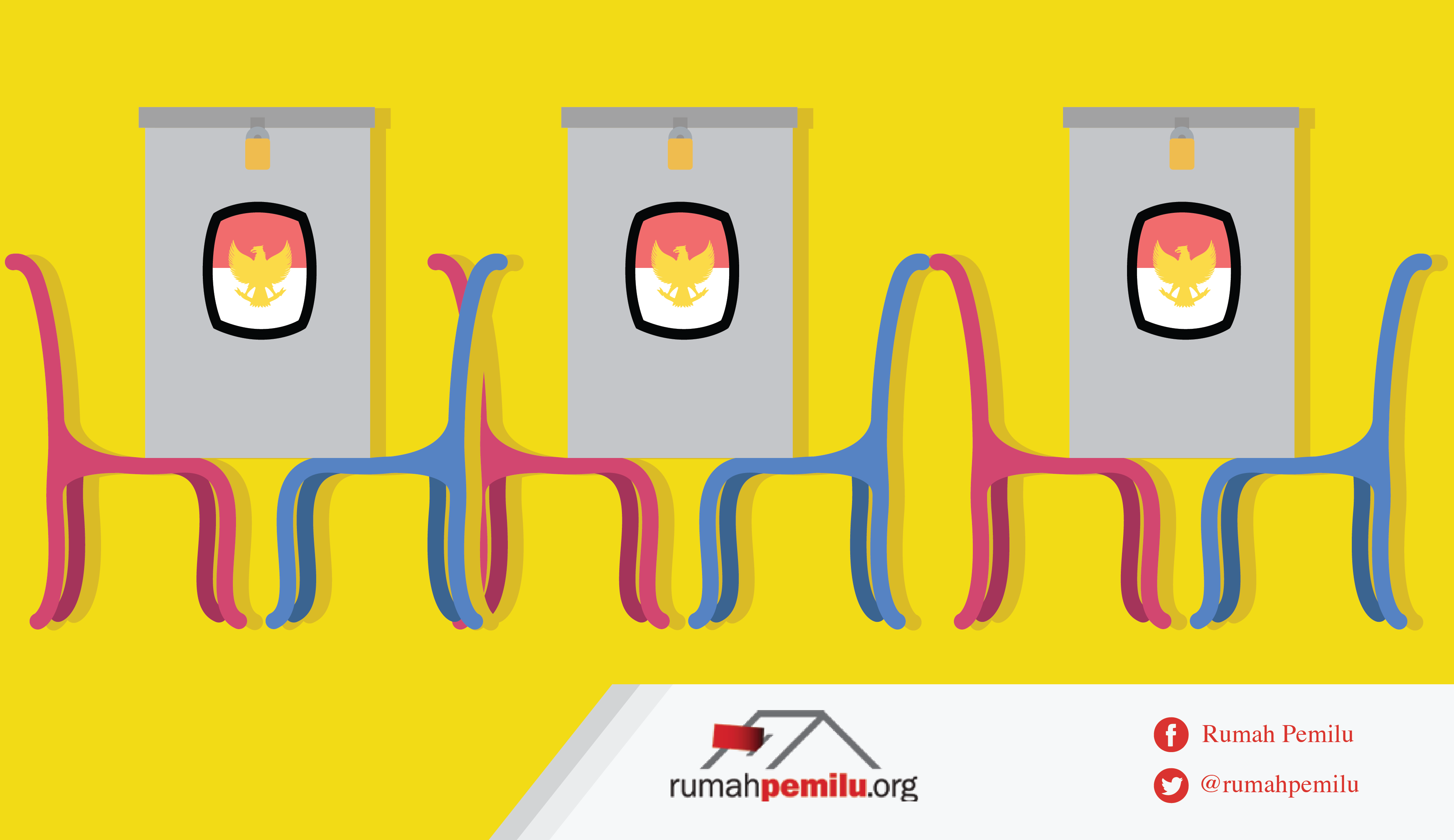Beberapa jenderal militer/ polisi dan birokrat provinsi rela melepas jabatan untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada 2018. Demikian juga sejumlah dandim, kapolres, dan sekda kabupaten/kota mau menanggalkan jabatan demi memburu kursi bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota.
Pelepasan jabatan penting di lingkungan TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) tersebut sebetulnya bukan gejala baru. Pada Pilkada 2015, misalnya, terdapat delapan perwira TNI/ Polri dan 176 petinggi ASN yang ikut berkompetisi merebut jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Malah pada Pilkada 2017 masyarakat dikejutkan oleh mundurnya perwira moncer, Mayor Agus Harimurti Yudhoyono, dari dunia militer demi mengikuti Pilkada DKI Jakarta.
Menduduki jabatan politik adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Meski demikian, hasrat anggota TNI/Polri/ ASN untuk menduduki jabatan- jabatan politik tersebut perlu diatur kembali. Bukan untuk melarang mereka memasuki dunia politik, melainkan untuk menentukan waktu terbaik: kapan dapat mengikuti perebutan jabatan politik. Oleh karena itu, beberapa pertimbangan perlu diperhatikan.
Tiga pertimbangan
Pertama, keluarnya anggota TNI/Polri/ASN sebelum masa pensiun jelas merugikan institusi negara yang ditinggalkan. Mereka telah dididik, dilatih, dan dibesarkan institusi negara agar jadi aparat yang tangguh dan profesional. Tidak sedikit dana negara yang dikeluarkan, tetapi ketika institusi negara masih butuh pikiran dan tenaganya, mereka justru pergi.
Lebih dari itu, mundurnya anggota TNI/Polri/ASN demi kontestasi politik telah menimbulkan kerusakan sistemik terhadap institusi negara yang ditinggalkannya. Sadar atau tidak, mereka memanfaatkan jaringan militer/kepolisian/birokrasi guna mendulang suara. Secara langsung atau tidak, mereka menyeret institusi negara ke dalam situasi tidak netral dalam kompetisi politik. Kerugian negara dan kerusakan sistemik harus segera dihentikan.
Kedua, perubahan tiba-tiba dari dunia militer/kepolisian/ birokrasi ke dunia politik adalah masalah serius. Kemampuan di jabatan militer/kepolisian/birokrasi bukan jaminan sukses saat memegang jabatan politik. Lingkungan kerja, sistem manajemen, serta target dan tujuan yang berbeda butuh keterampilan dan gaya kepemimpinan berbeda pula. Demi mencapai keberhasilan politik, kemampuan manajerial dan bakat kepemimpinan harus disesuaikan dengan iklim dunia politik.
Tanpa adanya masa penyesuaian, para mantan pejabat militer/kepolisian/birokasi yang menduduki jabatan politik akan terjebak pragmatisme politik dalam menjaga kekuasaannya. Selain itu, kultur militer/kepolisian/birokrasi yang selalu taat prosedur sehingga cenderung mempertahankan status quo membuat mereka miskin inovasi dalam memimpin lembaga pemerintahan. Itulah sebabnya jarang sekali terdengar kisah sukses mantan tentara/polisi/ birokrat dalam memimpin pemerintahan demokratis.
Ketiga, konstitusi memberikan peran sentral kepada partai politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Namun, kegagalan atau kesulitan dalam kaderisasi mendorong parpol menempuh jalan pintas: mengajukan pejabat militer/kepolisian/birokrasi sebagai calon pejabat eksekutif ataupun calon anggota legislatif. Pertimbangan lain, para pejabat tersebut memiliki modal cukup untuk bertarung dalam pemilihan. Jika pun kalah, organisasi sudah memperoleh dana, demikian juga pemimpin partai sudah kecipratan setoran.
Pola perekrutan politik seperti itu berlangsung sejak Pemilu 1999 dan terus menguat setelah Pilkada 2005. Kaderisasi jalan pintas tak hanya merusak kredibilitas parpol, juga menghambat pembangunan demokrasi. Demokrasi yang mengedepankan prinsip supremasi sipil tidak melarang mantan pejabat militer/kepolisian/birokrasi berkiprah di dunia politik, tetapi menempatkan lembaga politik (legislatif dan eksekutif) sebagai pemegang otoritas tertinggi dan bebas dari pengaruh militer/kepolisian/birokrasi.
Hal itu berarti sebelum jadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif, (mantan) pejabat militer/kepolisian/birokrasi harus memutus hubungan dengan institusi yang dipimpin sebelumnya. Selanjutnya, mereka harus menjalani penyipilan yang cukup sehingga kehadirannya sebagai pejabat politik tak mengancam, tetapi memperkuat demokrasi.
Masa jeda
Atas tiga pertimbangan tersebut, maka perlu dibuat peraturan guna mencegah anggota TNI/Polri/ASN jadi calon anggota legislatif ataupun eksekutif. UU Pemilu (dan pilkada) sudah mengatur hal itu, yakni mengharuskan anggota TNI/Polri/ ASN mengundurkan diri setelah mereka ditetapkan sebagai calon anggota legislatif ataupun eksekutif. Namun, ketentuan ini belum cukup karena pengunduran diri sesaat setelah penetapan calon masih menyisakan pengaruh mereka di institusi yang ditinggalkannya.
Yang harus dilakukan adalah memberikan jeda waktu buat mantan anggota TNI/Polri/ASN sebelum menduduki jabatan politik. Misalnya, mereka baru diperbolehkan jadi calon anggota legislatif atau eksekutif setelah lima tahun terhitung sejak tak lagi jadi anggota TNI/Polri/ ASN. Kurun waktu lima tahun ini cukup untuk menghapus pengaruh mereka di institusi yang ditinggalkannya, sekaligus cukup untuk menyesuaikan diri di lingkungan politik, misalnya dengan jadi pengurus parpol. Situasi itu juga bisa mencegah partai politik menempuh kaderisasi jalan pintas.
Pemberian jeda waktu beberapa tahun kepada mantan anggota militer dan birokrasi sebelum jadi pejabat politik sebetulnya sudah lazim di negara demokrasi. Oleh karena itu, demi pembangunan demokrasi, khususnya dalam menjunjung prinsip supremasi sipil, menjaga netralitas TNI/Polri/ASN, dan penguatan parpol, maka sudah seharusnya kita tidak ragu lagi membuat peraturan tersebut.
Didik Supriyanto, Kolumnis dan Peminat Masalah Pemilu
Dikliping dari artikel yang terbit di harian Kompas edisi 19 Februari 2018 di halaman 7 dengan judul “Melanjutkan Reformasi TNI/Polri dan Birokrasi”. https://kompas.id/baca/opini/2018/02/19/melanjutkan-reformasi-tnipolri-dan-birokrasi/
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal