Kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan pemberantasan korupsi boleh jadi merupakan sedikit hal yang masih dapat kita banggakan sebagai bangsa. Pada urusan lain, lebih banyak kisah ketertinggalan yang kita dengarkan. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menunjukkan kejengkelannya terhadap ketidakmampuan kita dalam menangkap peluang investasi asing.
Sektor pertanian dan manufaktur kita kian tertinggal bahkan dibandingkan Vietnam. Dalam urusan pengembangan SDM, kita juga jalan di tempat ketika negara tetangga terus menunjukkan lompatan kemajuan. Pun demikian dengan urusan olahraga. Di episentrum perolahragaan nasional, Istora Bung Karno, timnas kita baru saja dipermalukan beruntun oleh timnas negara tetangga.
Permasalahannya, menjaga tiga kebanggaan nasional yang tersisa itu pun nampaknya tak lagi menjadi prioritas. Revisi UU KUHP dan UU KPK menghadirkan arus-balik. DPR mengejar tenggat waktu pengesahan akhir September 2019. Sementara masyarakat sipil dan komunitas pers melihat ancaman nyata terhadap tiga hal di atas dalam revisi UU tersebut.
Permasalahannya, menjaga tiga kebanggaan nasional yang tersisa itu pun nampaknya tak lagi menjadi prioritas.
Muncul tanda-tanda, DPR akan lenggang-kangkung dengan agenda dan keyakinannya sendiri. Para wakil rakyat tak segan-segan memunggungi aspirasi masyarakat dan merasa absah membuat keputusan secara arbitrer. Resiproksitas antara keputusan wakil rakyat dan suara rakyat tak jadi pertimbangan. Pupus sudah kemesraan wakil rakyat dan yang diwakilinya seperti terlihat dalam perhelatan pemilu yang belum lama berlalu.
Tahta kosong untuk siapa?
Drama RUU KPK dan RUU KUHP mengingatkan kita pada telaah Claude Lefort dalam buku Democracy and Political Theory (1988). Lefort menjelaskan demokrasi sebagai problem mengisi ruang kosong (empty-space) yang telah ditinggalkan para raja dan penguasa despotik dalam model kekuasaan tradisional. Demokrasi adalah upaya membuat politik sebagai sistem yang rasional, transparan dan terkendalikan.
Melalui pemilu, demokrasi berupaya melengserkan sosok penguasa yang menganggap diri sebagai jelmaan seluruh rakyat sehingga setiap tindakannya adalah benar dan tak ada ruang untuk mempermasalahkannya. Telah diturunkan dari singgasananya, para penguasa tradisional pemegang otoritas metafisik-teologis yang kekuasaannya tidak tersentuh oleh siapa pun dan tidak merujuk pada kriteria legitimate-ilegitimate. Melalui pemilu, demokrasi berupaya menghadirkan kekuasaan semua orang, bukan kekuasaan satu atau sedikit orang.
Pupus sudah kemesraan wakil rakyat dan yang diwakilinya seperti terlihat dalam perhelatan pemilu yang belum lama berlalu.
Namun, bagaimana kita kemudian membayangkan kekuasaan oleh semua orang? Siapa yang akan menduduki tahta kosong yang ditinggalkan penguasa tradisional? Rezim totaliter berusaha mengambil alih tahta kosong itu. Totalitarianisme merupakan pembalikan sejarah untuk mewujudkan kembali identifikasi absolut penguasa dengan yang dikuasai (representation of the people-as-one) dengan memberangus keberagaman kehendak masyarakat sebagaimana hendak dilembagakan dalam demokrasi. Pada gradasi yang berbeda, rezim demokrasi menurut Lefort juga mengidap kecenderungan serupa.
Dalam rezim demokrasi, tahta-kosong itu tak pernah sungguh-sungguh diduduki rakyat. Kenyataan menunjukkan rakyat hanya menggenggam kedaulatan politik ketika pemilu berlangsung. Selanjutnya, kedaulatan itu berpindah-tangan ke para penguasa resmi yang kemudian lebih banyak bertindak secara instrumentalistik untuk memenuhi kepentingan partikularnya sendiri tanpa sungguh-sungguh menimbang kepentingan orang banyak.
Ruang kosong yang dilahirkan demokrasi tidak pernah benar-benar menjadi ruang bagi semua orang untuk mewujudkan kedaulatan diri. Gambaran tentang negara, wakil rakyat, partai politik yang bertindak atas nama kepentingan bersama begitu cepat menguap. Selebihnya, elite politik lebih menunjukkan diri sebagai individu atau kelompok dengan minat utama mempertahankan kepentingan ekonomi atau politik.
Dalam rezim demokrasi, tahta-kosong itu tak pernah sungguh-sungguh diduduki rakyat.
Maka tak mengherankan jika begitu pilpres 2019 selesai, partai politik pada merajuk meminta jatah kursi kabinet ke presiden terpilih. Partai yang kalah pemilu pun mencoba loncat pagar ke koalisi pendukung presiden terpilih. Dapat dibayangkan kekecewaan perasaan pemilih yang menganggap perkubuan politik sebagai sesuatu yang ideologis dan permanen. Tidak jelas pula siapa yang sesungguhnya memenangkan pemilu dan apa arti kemenangan itu. Pemilu sebagai sesuatu yang luhur akhirnya hanya tampak sebagai panggung bagi para oligark untuk memposisikan diri dalam orbit kekuasaan.
Mengapa kita seperti tidak mengenal kata jera dan tak sungguh-sungguh belajar dari pengalaman sejarah?
Keterbatasan imajinasi politik
Permasalahannya barangkali adalah keterbatasan imajinasi kita tentang bagaimana kekuasaan semestinya dijalankan. Praktik bagi-bagi kursi kekuasaan dan jual-beli pasal UU cenderung didiamkan karena memang seperti itulah kelaziman politik dalam benak masyarakat. Masyarakat tak memiliki gambaran lain tentang bagaimana politik dijalankan di luar apa yang sedang dijalankan para politisi. Jacques Ranciere dalam buku On the Shores of Politics (2007) menjelaskan esensi dari demokrasi perwakilan adalah upaya negara mendorong masyarakat melakukan penjarakan-diri terhadap politik (self-distancing of the political).
Mengapa kita seperti tidak mengenal kata jera dan tak sungguh-sungguh belajar dari pengalaman sejarah?
Konsekuensinya kemudian, imajinasi masyarakat tentang hak politik warga negara sebatas penyaluran suara dalam pemilu. Bagaimana suara itu kemudian berdampak pada kebijakan dan keputusan politik sepenuhnya diserahkan pada elite politik.
Ranciere dalam buku Hatred of Democracy (2016) menjelaskan demokrasi sebagai sebentuk anarki. Demokrasi menganulir bentuk pemerintahan yang pernah ada sebelumnya, sementara bentuk pemerintahan baru yang dibayangkan sesungguhnya tak memiliki dasar empiris-historis, yakni pemerintahan berdasarkan kerumunan orang.
Dengan getir Ranciere menjelaskan, demokrasi adalah pelaksanaan kekuasaan oleh rakyat ketika rakyat sendiri tidak memiliki referensi dan pengalaman tentang pelaksanaan kekuasaan secara kolektif. Demokrasi pada gilirannya adalah pelaksanaan hak rakyat untuk memerintah yang terjadi dalam konteks absennya hak untuk memerintah karena pemberlakuan sistem perwakilan rakyat.
Demokrasi menganulir bentuk pemerintahan yang pernah ada sebelumnya, sementara bentuk pemerintahan baru yang dibayangkan sesungguhnya tak memiliki dasar empiris-historis, yakni pemerintahan berdasarkan kerumunan orang.
Yang terjadi kemudian adalah demokrasi sebagai apropriasi atas oligarki. Demokrasi keterwakilan menurut Ranciere tak lain prosedur yang melegitimasi struktur kekuasaan oligarkis. Parpol membuat UU pemilu. Mereka jadi peserta pemilu. Mereka pula yang menikmati hasil pemilu. Selebihnya, masyarakat hanya jadi penonton penyelenggaraan kekuasaan hingga pemilu berikutnya tiba.
Demokrasi menurut Ranciere menghasilkan efek rekonsolidasi batas-batas urusan privat dan publik. Parpol mengejar kursi menteri dan menentukan pimpinan KPK sedemikian rupa seakan-akan keduanya adalah urusan privat mereka. Urusan privat yang diputuskan melalui negosiasi antar parpol tanpa sungguh-sungguh menimbang rekam-jejak, kelayakan dan persetujuan publik. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pengulangan: penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan proyek-proyek pemerintah juga diperlakukan sebagai urusan pribadi pejabat atau politisi.
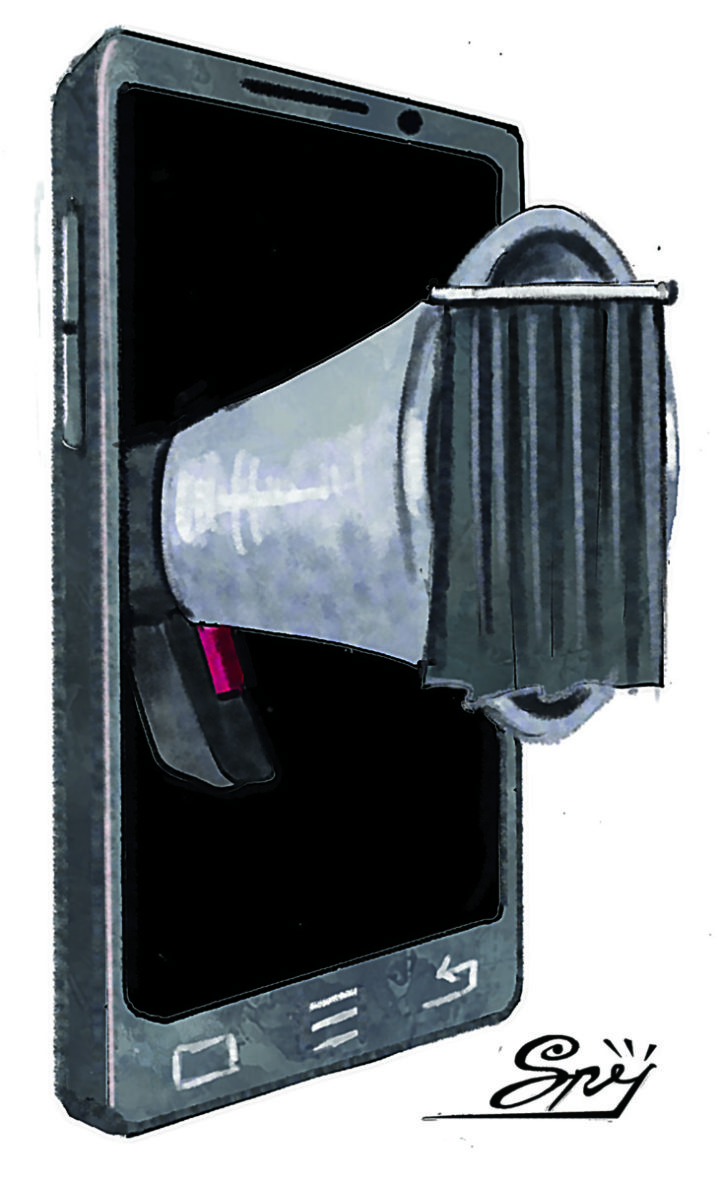
Lalu bagaimana kita dapat memutus siklus oligarki politik itu? Tak ada jawaban memuaskan. Namun, setidak-tidaknya dapat dinyatakan perlunya penanaman terus-menerus imajinasi kolektif tentang politik yang melampaui urusan pemilu. Politik juga mencakup urusan bagaimana kekuasaan diselenggarakan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Urusan ini bahkan bisa lebih penting dari urusan pemilu. Oleh karena itu, spektrum partisipasi politik perlu diperluas dari sekadar urusan ikut dan mengawal pemilu.
Demokrasi keterwakilan menurut Ranciere tak lain prosedur yang melegitimasi struktur kekuasaan oligarkis.
Partisipasi politik juga menuntut keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, dengan melakukan pengawasan, menjalankan kritik dan menggerakkan wacana publik yang terbuka. Imajinasi seperti ini tentu tidak baru sama sekali. Namun, menjadi relevan untuk ditekankan kembali tatkala belakangan ini masyarakat memperoleh perangkat yang sangat menjanjikan terkait partisipasi politik warga negara: media sosial.
Medsos adalah harapan baru bagi perwujudan hak politik warga negara secara lebih bermakna. Keterbukaan yang dibawa medsos menyulitkan para pemimpin menyembunyikan muslihat dan keingkaran. Medsos memungkinkan semua orang bertindak secara politis, tanpa terhalang hierarki sosial. Semestinya medsos lebih operasional sebagai sarana deliberasi politik, alih-alih sebagai sarana penyebaran kebohongan dan permusuhan. Sungguh disayangkan wacana kritis di medsos yang begitu semarak saat menjelang pemilu belakangan meredup ketika pemilu berlalu. Hal ini sama saja dengan memberi peluang pada para oligark yang ingin menyerobot panggung politik untuk dirinya sendiri dan mengabaikan para pemilih.
Medsos memungkinkan semua orang bertindak secara politis, tanpa terhalang hierarki sosial.
AGUS SUDIBYO, Head of New Media Research Center ATVI Jakarta
Diklping dari artikel yang terbit di harian Kompas edisi 17 September 2019 di halaman 6 dengan judul “Panggung Oligarki Politik”. https://kompas.id/baca/utama/2019/09/17/panggung-oligarki-politik/
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal




