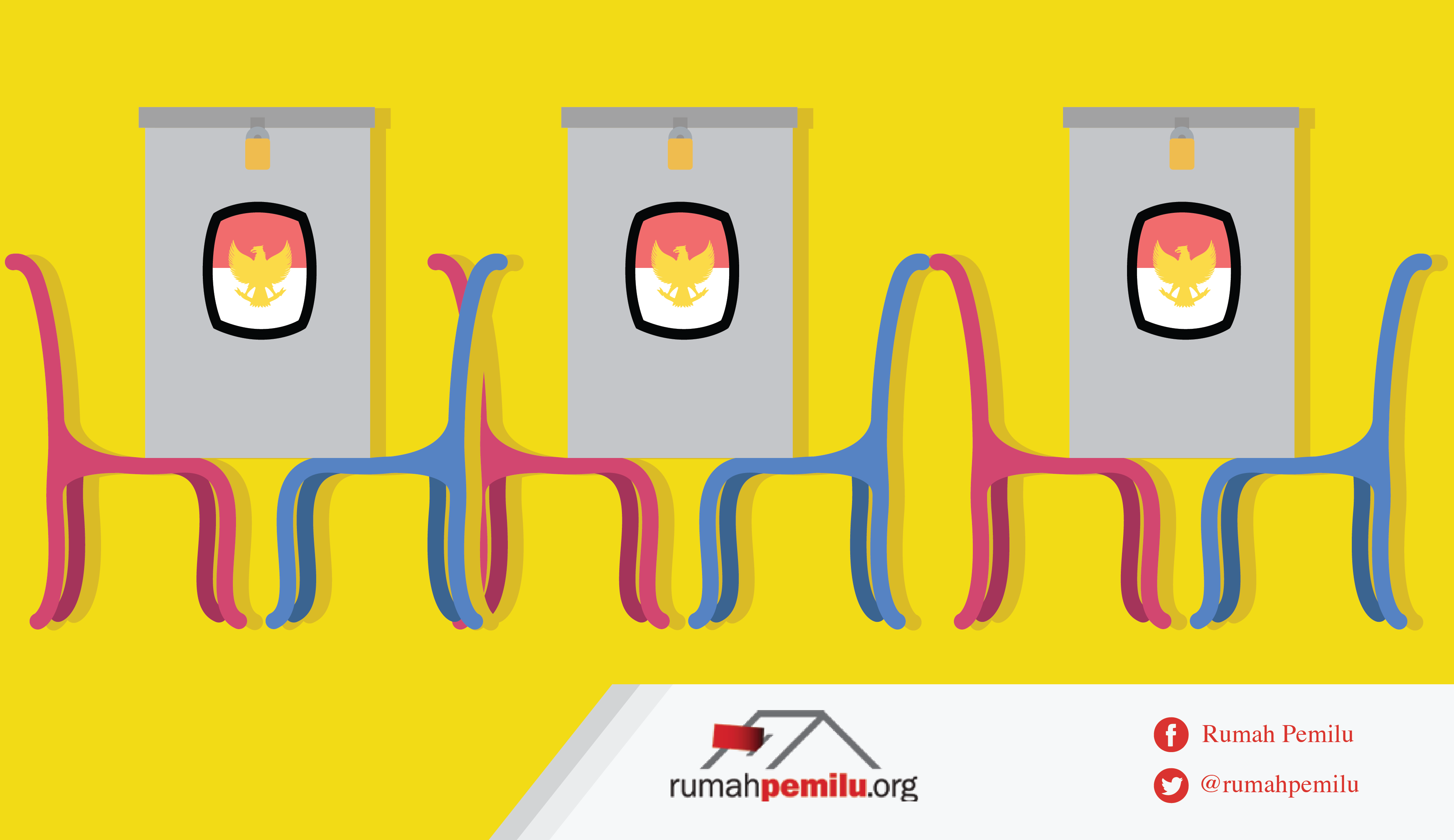DPR menyoroti kemandirian KPU—sayangnya bukan dalam rangka memilih mereka yang bebas intervensi, tapi untuk mengkonfrontasi “kenakalan” KPU.
Kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling disorot oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU 2017-2022. Soal ini terus mencuat dalam rapat-rapat Komisi II DPR sejak KPU mengajukan uji materi tentang ketentuan pasal di UU Pilkada yang mewajibkan penyusunan peraturan KPU melalui konsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat.
“Definisi KPU yang independen dan mandiri itu membuat KPU tak ada hubungan dengan partai. Padahal KPU itu panitia pernikahan. Yang punya pesta pernikahan itu partai politik,” kata Komarudin Watubun, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, saat melakukan tanya jawab dengan calon anggota KPU di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta (3/4).
Arief Budiman, anggota KPU yang kembali mencalonkan diri, menegaskan bahwa kemandirian berkaitan dengan bagaimana cara KPU mengambil keputusan atau membuat kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan, KPU tentu terbuka pada semua pihak.
“Tapi ketika memutuskan, keputusan atau kebijakan itu dilaksanakan independen,” kata Arief.
Mandiri, independen, atau merdeka?
Rambe Kamarul Zaman, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, saat Arief menjawab pertanyaan, langsung memotong ketika Arief menyebut kata independen. “Dari mana itu independen? Jangan diucapkan lagi itu,” katanya.
Arief mengoreksi pernyataannya. Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar menyebut pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri—bukan independen.
Di tengah tanya jawab sesi pertama itu, Lukman Edy, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, juga memotong tanya jawab. Ia memberikan Salinan Undang-undang Dasar pada empat calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di sesi pertama itu.
“Saya berikan biar bisa membedakan mana merdeka, independen, mandiri,” kata Lukman pada hadirin sidang.
Konstitusi memang mengenal tiga istilah yang seolah serupa tapi tak sama. Frasa merdeka disebut dalam Pasal 24 ayat (1) Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Pasal itu berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,”
Frasa independen disebut dalam Pasal 23D pada Bab VIII tentang Hal Keuangan. Pasal tersebut berbunyi, “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.” Sementara frasa mandiri disebut dalam Pasal 22E ayat (5) tadi.
“Tolong calon ini membaca risalah lahirnya pasal-pasal ini sewaktu pembahasan perubahan UUD dari badan pekerja itu. Selama ada komisioner yang mau lanjut, ini harus selesai,” kata Rambe Kamarul Zaman.
Achmad Baidowi, anggota Komisi II dari Fraksi PPP, bahkan menilai KPU hendak menjadi pilar baru negara demokrasi yang ditopang pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Didik Supriyanto, pakar pemilu, dalam buku Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu menjelaskan, KPU sebagai lembaga mandiri di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif sah secara konstitusional.
Pasca runtuhnya Orde Baru, reformasi institusi dilakukan dan dibentuk lembaga baru yang independen. Dalam sistem masyarakat modern, juga dikenal teori politik atau hukum tata negara the auxiliary state agency. Teori ini menjelaskan adanya lembaga tambahan dalam pemerintah. Sistem pembagian kekuasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak memadai lagi sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara tambahan.
Fadli Ramadhanil, peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menegaskan, jika dilacak dari perdebatan pembahasan ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, kata mandiri itu muncul karena para pengubah UUD 1945 ingin mensterilkan KPU dari intervensi terutama kepentingan politik dan penguasa.
Ia mengurai, keinginan adanya suatu lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri muncul setelah pelaksanaan Pemilu 1999. Penyelenggara Pemilu 1999 terdiri dari utusan pemerintah dan utusan partai politik peserta pemilu. Hal ini membuat membuat lembaga penyelenggara pemilu syarat dengan tarik ulur kepentingan politik.
“Puncaknya, anggota KPU dari utusan partai politik menolak menetapkan hasil Pemilu 1999, karena mendalilkan terjadi kecurangan, dan partai politik mereka dirugikan dengan hasil pemilu,” kata Fadli.
RDP mengikat dan ujian kemandirian
Perdebatan soal definisi mandiri yang melekat pada KPU telah muncul lama sejak Pasal 9 huruf a UU 10/2016 memuat ketentuan: tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Perdebatan kian meruncing saat KPU mengajukan uji materi pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketentuan ini dinilai mengganggu kemandirian KPU dalam mengambil keputusan. Rapat dengar pendapat sering diwarnai perdebatan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan fraksi. KPU risau jika harus mengikuti hasil rapat ini.
“Nanti kalau itu dijalankan diduga berpihak kepada fraksi yang mengusulkan itu. KPU merasa lebih nyaman bisa menyimpulkan itu mandiri,” kata Arief dalam uji kelayakan dan kepatutan.
Sementara Evi Novida Ginting, anggota KPU Sumatera Utara yang mencalonkan diri sebagai anggota KPU RI, berpendapat, KPU dan DPR adalah mitra kerja yang perlu kerja sama dan komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas.
“Dukungan kuat dibutuhkan tanpa mengganggu integritas dan independensi,” kata Evi.
Wahyu Setiawan bersikap lain. Ia berani mengundurkan diri jika KPU melakukan judicial review kembali. Sikap ini, menurutnya, adalah penghormatan pada lembaga negara dan peraturan perundang-undangan.
“Jika ada judicial review dan saya kalah di rapat pleno KPU maka saya akan mengundurkan diri,” kata Wahyu Setiawan yang juga menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU di DPR (4/4).
Sikap ini ia cetuskan setelah Komarudin Watubun, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, menantang pernyataan Wahyu soal komitmen menciptakan hubungan baik Komisi II dengan KPU. Wahyu memandang rapat konsultasi adalah ajang yang baik untuk bertarung dan bertempur gagasan dalam rangka pembentukan peraturan KPU di bawah undang-undang.
Ia tak setuju atas sikap pengajuan judicial review terkait ketentuan di Pasal 9 UU Pilkada yang mewajibkan penyusunan peraturan KPU melalui konsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat. Ia memandang, keputusan rapat konsultasi ini harus dihormati.
“Untuk menguji ketegasan Saudara, saya mau tanya. Kalau besok KPU baru nanti melakukan judicial review lagi, akan melakukan sikap keluar dari KPU?” tanya Komarudin.
Pertanyaan itu dijawab dengan tegas dan lugas oleh Wahyu, “Berani.” Kemudian tepuk tangan bergemuruh di ruang rapat Komisi II itu.
Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, menilai uji materi yang dilakukan KPU sah secara konstitusional. Titi membantah pendapat yang menilai tak wajar KPU sebagai penyelenggara pemilu menggugat undang-undang pilkada.
“Gugatan uji materi soal kemandirian penyelenggara pemilu ini adalah hal konstitusional dan demokratis,” kata Titi Anggraini.
Rambe Kamarul Zaman sependapat. Ia juga tak menilai salah apa yang dilakukan KPU. Namun, menurutnya, keberanian KPU mengajukan uji materi tak baik secara etika politik, sebab KPU adalah mitra Komisi II DPR RI. “Sebenarnya tidak salah, silakan, tapi etikanya bagaimana?” tandas Rambe.
Kemandirian adalah muruah KPU yang tak bisa ditawar-tawar. Terlalu besar pertaruhan jika proses seleksi penyelenggara pemilu hanya jadi ajang adu kuat antarfaksi politik dan tawar-menawar kepentingan untuk mengokohkan pengaruh. Selain itu, jangan sampai DPR meloloskan calon-calon yang gencar melakukan lobi-lobi politik. Sebab, perilaku itu lebih cocok dimainkan politisi peserta pemilu ketimbang calon penyelenggara. Perilaku seperti ini orientasinya bukan lagi bergiat dan mengabdi, tapi sudah bergeser demi mengejar jabatan dan saluran menuju kuasa. Penyelenggara pemilu yang baik, akan mengedepankan kepakaran dan rekam jejak sebagai “pengaruh” untuk memastikan keterpilihannya.
“Kalau DPR sampai memilih para lobbyst (pelobi) maka saat yang sama kita bersiap mempertaruhkan penyelenggaraan pemilu pada para penyelenggara bermental petualang politik. Mereka akan menyemarakan pemilu dan demokrasi sebagai arena yang kental politik transaksional. Terlalu mahal harga yang harus kita bayar untuk itu,” tandas Titi.
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal