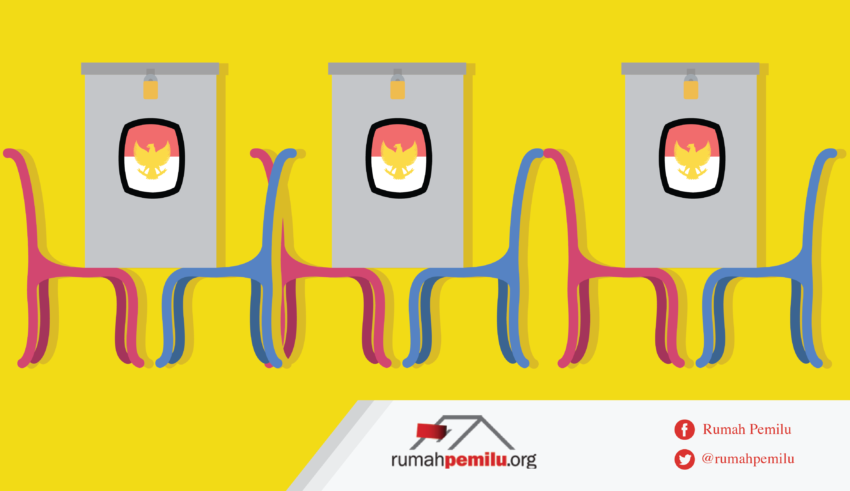Terkait keserentakan pemilu, argumen utama yang eksplisit disebut dalam putusan MK adalah bagaimana memperkuat sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilihan dari sisi anggaran, waktu dan pengelolaan konflik. Pemikiran tersebut ada benarnya sebab dalam empat kali pemilu (1999, 2004, 2009 dan 2014) pemerintahan yang terbentuk hanya menghasilkan pemerintah minoritas (minority government). Presiden terpilih berasal dari partai yang tidak meraih suara terbanyak di DPR (Harun Husein, 2014: 523). Dalam konteks ini, mengapa desain keserentakan pemilu perlu dievaluasi dan bagaimana korelasinya dengan upaya memperkuat sistem presidensil.
Dalam gelar perkara uji materi No.16/2021 di Mahkamah Konstitusi mengenai desain pemilu serentak, Senin (27/9/2021), Majelis MK meminta pendapat ahli terkait rekayasa teknis yang mungkin dilakukan apabila pemilu dilaksanakan dengan serentak yakni pemilihan umum presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa Mahkamah ingin mendapatkan penjelasan dari ahli, apabila jumlah penyelenggara pemilu ditambah untuk mengantisipasi kelelahan beban pada pelaksanaan pemilu serentak mendatang.
Merespons hal itu, salah satu dari tiga ahli yang dihadirkan pemohon yakni Anggota Dewan Pembina Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan penambahan petugas penyelenggara di tiap tingkatan mulai dari panitia penyelenggara pemungutan suara (PPPS) hingga petugas di kabupaten/kota, akan berdampak pada banyak hal. Titi menuturkan, ketika memecah lima perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) secara pararel, di saat yang sama harus ada lima saksi partai, lima pengawas TPS dan tempat yang besar yang berimplikasi membawa politik biaya tinggi pada pemilu.
Titi mengatakan pilihan penjadwalan pemilu serentak yang menggabungkan pemilu DPR dan DPRD provinsi, kabupaten/kota serta DPD dalam satu jadwal, mengakibatkan kompleksitas dan kerumitan teknis. Bahkan, menurutnya mendistorsi azas kedaulatan rakyat. Penggabungan pemilu tersebut, ujar Titi, telah dilakukan sejak 2004 dengan kombinasi sistem pemilu proposional terbuka. Pemilu yang serentak, imbuhnya, mengakibatkan tingginya surat suara tidak sah melampaui rata-rata global yaitu dari 4%. Bahkan pada pemilu 2019 mencapai 11,12%.
Suara tidak sah dalam pemilu 2019 disebabkan oleh sejumlah alasan antara lain karena besarnya surat suara disebabkan sistem proporsional yang memuat daftar calon anggota DPR, DPD dan DPRD, berubahnya kriteria surat suara, dan minimnya pengetahuan pemilih mengenai teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara (Harun Husein, 2014: 327).
Dengan kata lain, suara tidak sah merupakan pemenang Pemilu ketiga setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dari gambaran itu, saya berpendapat mesti ada perubahan dalam penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini bukan sistem pemilunya, tetapi desain keserentakan pemilu, agar pemilu merefleksikan kehendak rakyat secara murni.
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu antusiasme pemilih terhadap Pilpres terbilang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari tingginya partisipasi pemilih yang mencapai 81,93 % dan suara sah yang lebih besar dari suara sah Pileg pada gelaran pemilu serentak 2019 lalu. Pada pemilu serentak tahun 2019 jumlah suara sah untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu 154.257.601. Artinya ada kenaikan dari sebelumnya, yaitu pada Pilpres 2014 yang hanya 133.574.277. Sementara pada level Pileg, jumlah suara sah juga mengalami peningkatan dari 124.972.491 pada Pileg 2014 menjadi 139.971.260 pada pemilu serentak 2019.
Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa, suara sah yang besar pada surat suara Pilpres dibandingkan dengan surat suara pada Pileg dapat dibaca sebagai gejala bahwa, panggung Pilpres jauh lebih “seksi” ketimbang Pileg. Argumen ini diperkuat oleh temuan Charta Politika yang dirilis sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, pada April yang lalu, di mana 75,4 persen dari 800 responden yang disurvei menjawab akan memilih kertas suara Pilpres terlebih dahulu.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa, Pileg 2019 cenderung “diabaikan” masyarakat karena euforia kontestasi Pilpres 2019 yang ketat dan sengit. Ada pula sejumlah hal lain yang masih menyisakan persoalan, misalnya rumitnya proses administrasi Pemilu Serentak 2019, banyaknya korban penyelenggara pemilu yang meninggal akibat kelelahan, hoaks dan politik identitas yang meningkat serta masalah-masalah klasik pemilu lainnya.
Pilihan atas format pemilu semestinya merupakan satu kesatuan rangkaian paket pilihan bersama-sama dengan sistem pemerintahan, sistem perwakilan, dan sistem kepartaian. Artinya, harus ada koherensi dan konsistensi antara pilihan atas sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem pemilu, dan sistem kepartaian. Karena itu pilihan atas format dan sistem pemilu semestinya bertolak dari kesepakatan tentang tujuan berpemilu itu sendiri, apakah lebih pada tujuan pertama yakni representativeness atau keterwakilan politik semua unsur, kelompok, dan golongan dalam masyarakat, atau lebih pada tujuan kedua yaitu menghasilkan pemerintah yang bisa memerintah atau yang populer disebut sebagai pemerintahan yang efektif.
Dalam praktiknya, Pemilu Serentak 2019 tidak memiliki keterhubungan dimaksud, karena masing-masing sistem bekerja sendiri-sendiri. Bahkan ada kesulitan misalnya model kertas suara (ballot) juga tidak sinergis tetapi terpisah-pisah. Hampir muskil menjadikan model kertas suara perihal pemungutan dan penghitungan suara berdampingan antara calon presiden/wakil presiden dengan calon anggota DPR. Hal itu diakibatkan penerapan sistem proporsional terbuka yang menyulitkan dalam pembuatan desain kertas suara yang diharapkan tidak berbeda, tetapi pada kertas yang sama.
Rumit dan banyaknya jenis surat suara menyebabkan pemilih bahkan kesulitan dalam menentukan pilihan, dan jeda waktunya cukup panjang dari satu pilihan ke pilihan lainnya. Dalam praktiknya, sistem berjalan sendiri-sendiri tidak ada keterhubungan sama sekali satu dengan lainnya. Dalam konteks keterhubungan antar sistem juga dilihat dari sisi substansi dan sistem kepartaian yang dihasilkan oleh pemilu.
Beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh para ahli menyebut bahwa kombinasi sistem pemilu proporsional, multipartai dan presidensial, seperti yang dilakukan oleh Mainwaming dan Scully (1955) menyebut bahwa ketiga kombinasi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Salah satu masalahnya, pemilu tidak menghasilkan kekuatan mayoritas, bahkan partai minoritas berpeluang atau dapat memenangkan pilihan presiden. Juga terdapat kesulitan-kesulitan dalam membentuk pemerintahan yang kuat atau efektif, karena kesulitan koalisi. Linz dan Stepan (1996) menyebut, dalam presidensial tidak ada watak koalisi seperti dalam parlementer. Kecenderungan presidensial yang rentan dalam merinci demokrasi, dianggap menimbulkan ketidakstabilan.
Gambaran Pemilu 2019 di atas menunjukkan bahwa perubahan skema pemilu, dari tidak serentak menjadi serentak hasilnya tetap sama. Artinya tidak terlalu ada perbedaan antara skema pemilu yang terpisah dengan yang diserentakkan, bahkan pemilu serentak model 5 kotak melahirkan kecenderungan pemilih terfokus pada pemilihan presiden dan wakili presiden, dan malah “menenggelamkan” esensi dari pemilu legislatif dan DPD. Dari sisi penyelenggaraannya pun terasa rumit dan kompleks, belum lagi dari sisi hasil pemilu yang kurang compatible untuk menghasilkan komposisi politik di satu sisi dan kekuatan politik di sisi lain yang dapat memperkuat sistem presidensial.
Secara teoretis, presidensialisme menjadi masalah kalau berkombinasi dengan sistem multipartai. Ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem presidensial diyakini semakin kentara bila dipadukan dengan sistem multipartai. Pengalaman di beberapa negara yang mampu membentuk pemerintahan yang stabil karena memadukan sistem presidensial dengan sistem dwi partai, bukan multipartai, contohnya Amerika Serikat.
Argumentasi terkait keserentakan pemilu memperkuat sistem pemerintahan presidensial, dan melahirkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilihan dari sisi anggaran, waktu dan pengelolaan konflik belum dapat terwujud dengan sungguh. Bahkan dari sisi anggaran di pemilu serentak 2024, lembaga penyelenggara Pemilu membutuhkan anggaran sebanyak Rp86 triliun. Anggaran yang dicanangkan KPU itu bisa diambil dari APBN 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025.
Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, dapat dibayangkan persoalan yang sama akan terjadi pada Pemilu 2024. Menurut saya, desain keserentakan dan sistem pemilu perlu dievaluasi kembali dan diarahkan ke upaya penyederhanaan partai politik demi mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, demokratis, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. []
FORTUNATUS HAMSAH MANAH
Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Provinsi NTT
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal