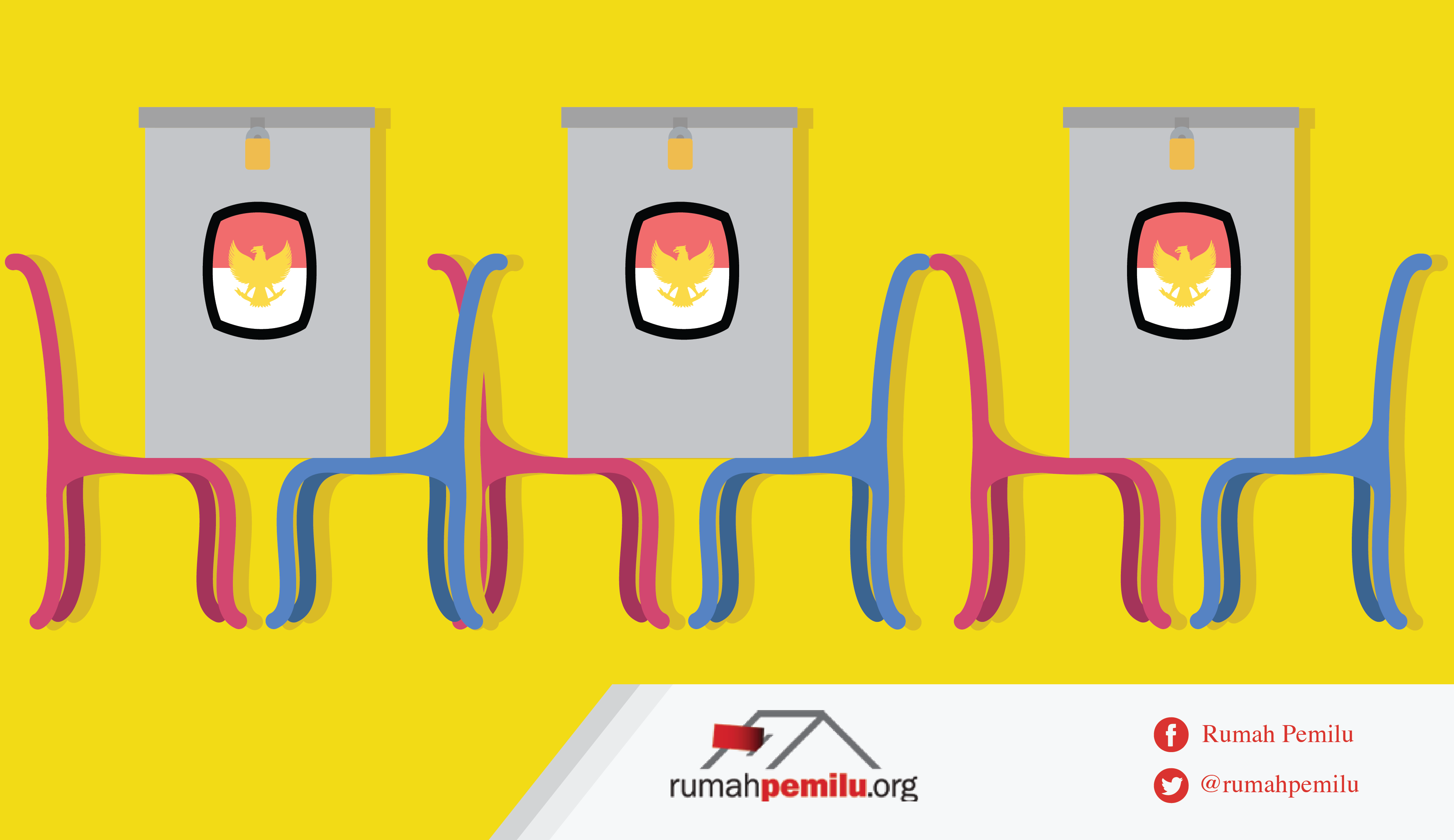Jokowi sibuk membangun infrastruktur fisik tapi melupakan pemilu sebagai infrastruktur mendasar dalam demokrasi. Ini dapat dilihat dari tiga kesalahan Jokowi dalam pembahasan RUU Pemilu: tak tepat waktu, tak paham politik kepemiluan, dan tak punya strategi memperjuangkan pilihan politiknya di DPR.
“Jokowi sibuk dengan infrastruktur. Dia lupa bahwa pemilu adalah infrastruktur demokrasi,” kata Syamsuddin Haris, profesor riset Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI), geram.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sibuk menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi abai terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada tiga kesalahan Jokowi yang jadi indikasi ia mengabaikan RUU Pemilu. Pertama, Jokowi telat mengajukan pembahasan RUU Pemilu ke DPR. Kedua, Jokowi tak paham politik kepemiluan. Ketiga, Jokowi tak punya strategi memperjuangkan pilihannya di DPR.
Telat
Jokowi baru meneken surat bernomor R-66/Pres/10/2016 dengan lampiran RUU Pemilu yang ditujukan pada Ketua DPR tanggal 20 Oktober 2016. Jokowi mengutus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM untuk terlibat dalam pembahasan bersama DPR.
“Kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibicarakan dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama,” kata Jokowi dalam surat berlogo Presiden Republik Indonesia yang didapat Rumah Pemilu (20/10).
Saat surat ini terbit, berbagai kalangan menilai Jokowi sudah sangat terlambat. Mari kita bandingkan. Pada Agustus 2015, Kemitraan (Partnership for Government Reform), merilis buku Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu dengan komando Ramlan Surbakti—Guru Besar Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. April 2016, Sekretariat Bersama (Sekber) untuk Kodifikasi UU Pemilu yang dihuni oleh berbagai organisasi masyarakat sipil telah merampungkan naskah akademik lengkap dengan pasal-pasalnya dalam buku Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.
Kemitraan dan Sekber ini juga telah berkeliling ke DPR dan Pemerintah untuk mempromosikan naskahnya serta mendesak mereka untuk menyegerakan pembahasan RUU Pemilu.
“Idealnya UU Pemilu selesai April 2017—24 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang diasumsikan diselenggarakan bulan April. Waktu pengesahan UU Pemilu yang terlalu dekat dengan pelaksanaan pemilu membuat jalannya pemilu berantakan,” kata Didik Supriyanto, Koordinator Sekber.
Nyatanya hingga Juni 2017 ini, DPR dan Pemerintah masih ngotot-ngototan mempertahankan posisinya dalam lima isu krusial: sistem pemilu, alokasi kursi per dapil, metode konversi suara jadi kursi, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), dan terutama ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
DPR selalu meleset dari target pengesahan RUU Pemilu. DPR sempat menargetkan pembahasan RUU Pemilu akan rampung pada 28 April 2017. Namun, target tersebut molor hingga 18 Mei 2017.
Di bulan Juni ini saja, DPR sudah melakukan penundaan hingga empat kali. Awalnya, pengambilan keputusan direncanakan pada 8 Juni, kemudian ditunda pada 13 Juni dan 14 Juni. Lalu, menurut rencana, pada hari ini (19/6) pengambilan keputusan itu akan dilakukan namun kembali ditunda. Pengambilan keputusan tingkat pertama di Pansus direncanakan tanggal 6 Juli 2017 dan paripurna penetapan RUU Pemilu akan dilakukan pada 20 Juli 2017.
Tak paham
Jokowi dinilai tidak punya politik kepemiluan yang jelas. Indikasi ini dapat terlihat dari naskah akademik RUU Pemilu yang diajukan pemerintah ke DPR. Naskah akademik tak mendedah secara utuh desain pemilu seperti apa yang diinginkan Jokowi.
Maka tak aneh jika sikap Pemerintah, dalam jalannya pembahasan RUU Pemilu, kerap berubah-ubah menyesuaikan keinginan partai-partai di DPR. Pemerintah, misalnya, mengajukan empat varian pilihan sistem pemilu: dari terbuka, tertutup, terbuka terbatas, hingga terbuka dengan modifikasi. Pilihan pemerintah dinilai tak disertai dengan argumen yang jelas.
“Saya sendiri gak tau yang nyusun itu siapa sehingga sampai pada naskah yang aneh itu. Jokowi tidak punya politik kepemiluan yang jelas. Pemerintahan Jokowi tidak cukup paham politik. Dia tidak punya tangan kanan menangani ini. Mungkin punya, tapi bukan pilihan pas,” kata Syamsuddin.
Yang paling mutakhir adalah soal ambang batas pencalonan presiden yang kerap disalahistilahkan menjadi presidential threshold. Mendagri yang teguh pada pendirian threshold 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara pemilih memancing pertanyaan publik: mengapa pemerintah ngotot memilih opsi ini dan siapa yang memerintahkannya untuk ngotot mempertahankan hal tersebut.
Kebingungan publik dipicu oleh pandangan bahwa ambang batas pencalonan presiden tak lagi relevan sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dilakukan serentak pada 2019. Jika serentak, tentu belum ada hasil pileg yang bisa dijadikan acuan presidential threshold.
Fadli Ramadhanil, peneliti hukum pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menegaskan, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu,” Partai yang menjadi peserta pemilu otomatis boleh mengajukan pasangan presiden meskipun tidak punya kursi di DPR.
“Bukan semua partai politik. Tapi partai politik yang sudah melakukan verifikasi oleh KPU, uji kelayakan, administrasi, dan faktual dan ditetapkan jadi peserta pemilu. Itu yang dimaksud pasal 6A,” kata Fadli.
Setelah ditunggu lama, Jokowi akhirnya buka suara soal presidential threshold. Ia mengaku telah menugaskan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengawal ketentuan ambang batas partai bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden tetap 20 persen.
“Politik negara ini akan semakin baik harus ada konsistensi, sehingga kita ingin kalau yang dulu sudah 20 (persen), masak kita mau kembali ke nol,” kata Jokowi, seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Minggu (18/6).
Mahfud MD, Ketua MK 2008—2013, menilai pandangan yang mengatakan bahwa presidential threshold bisa tetap diberlakukan muncul atas pembacaan terhadap Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang secara formal dan gramatikal hanya menyatakan bahwa Pileg dan Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara serentak di hari yang sama, tidak menyebutkan apakah harus menggunakan threshold atau tidak.
“Dari sudut ini bisa ditafsirkan bahwa masalah threshold merupakan opened legal policy, pilihan politik hukum terbuka, artinya bisa ditentukan oleh lembaga legislatif sendiri,” kata Mahfud sebagaimana dikutip dari opininya berjudul “Threshold Pilpres: Bisa Ya, Bisa Tidak” di Koran Sindo (17/6).
Hasil Pemilu 2014—oleh para pendukung threshold—dirasa bisa digunakan sebagai syarat pemenuhan threshold dengan alasan hasil Pemilu 2014 bisa dijadikan ukuran minimal bahwa partai-partai yang boleh mengajukan pasangan calon sudah terbukti punya dukungan dari rakyat melalui pemilu (sebelumnya).
Fadli tak sependapat. Menurutnya, hasil Pemilu 2014 tak lagi memperlihatkan dukungan riil rakyat di fase pemilu 2019. Selain itu, akan ada hak dan kesempatan yang tak seimbang antarpeserta pemilu, apalagi terhadap partai politik baru yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan menurut UUD punya hak yang sama untuk mencalonkan presiden.
Tak punya strategi
Jokowi juga tak punya strategi memadai untuk memperjuangkan pilihan politik kepemiluannya di DPR. Naskah RUU Pemilu yang disusun Pemerintah kerap dipasrahkan kepada kehendak politik partai-partai di DPR. Pemerintah seolah tak punya pendirian.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, yang jadi wakil pemerintahan Jokowi kerap memasrahkan pilihan politik isu-isu tertentu pada kehendak DPR. Setidaknya Tjahjo berkata “silakan, itu terserah DPR” pada tiga isu: verifikasi syarat partai politik peserta pemilu, afirmasi untuk keterwakilan politik, dan alokasi tambahan 15 kursi. Tjahjo hanya menyimpan satu isu saja yang tak boleh ditentukan oleh kehendak DPR: ambang batas pencalonan presiden 20—25 persen.
Soal ini, ia tak pernah mundur. Berbagai strategi dan manuver politik kerap dilakukan Tjahjo. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan kerap ditunda—bahkan hingga empat kali.
Manuver strategi Tjahjo beragam. Ia sempat tak hadir dalam rapat bersama DPR. Tjahjo berpandangan ketidakhadirannya hari itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyatukan pandangan. DPR diminta kembali melakukan lobi sehingga tercapai kesepakatan soal lima isu krusial jelang pengambilan putusan di tingkat pansus.
Esoknya, Pemerintah mewacanakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika pengesahan RUU Pemilu masih menemui jalan buntu. Substansi Perppu mengacu pada UU lama dengan perubahan pada konteks keserentakan pemilu. “Tidak ada yang prinsip kok. Hanya keserentakan saja. Serentak yang bagaimana apakah jam yang sama, hari yang sama, atau bulan yang sama,” kata Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta (14/6).
Tjahjo juga sempat mengancam untuk menarik diri dari pembahasan jika fraksi-fraksi di DPR tak menemui titik sepakat.
Kesalahan besar dalam strategi Jokowi adalah ketidakberhasilannya mengkonsolidasi partai pendukung pemerintah untuk memperjuangkan pilihan politiknya di DPR.
Dari awal pembahasan, klaim bahwa fraksi-fraksi partai koalisi solid menyikapi lima isu krusial—khususnya isu alot seputar ambang batas pencalonan presiden di RUU Pemilu—baru terjadi di akhir-akhir.
Sikap koalisi partai pendukung pemerintah awalnya terbelah. Hanya fraksi PDIP, Golkar, dan NasDem yang mendukung sikap pemerintah. Sementara empat fraksi lain, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Hanura menginginkan besaran ambang batas diubah. Keadaan inilah yang sempat membuat Mendagri mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu.
Sikap Jokowi, Mendagri, dan dinamika politik pada pembahasan RUU Pemilu menunjukkan bahwa Jokowi sibuk dengan infrastruktur fisik dan melupakan pemilu sebagai infrastruktur demokrasi. Ia lupa, tanpa pemilu yang baik dan berintegritas, demokrasi yang terkonsolidasi baik dan sehat tak mungkin dihasilkan.
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal