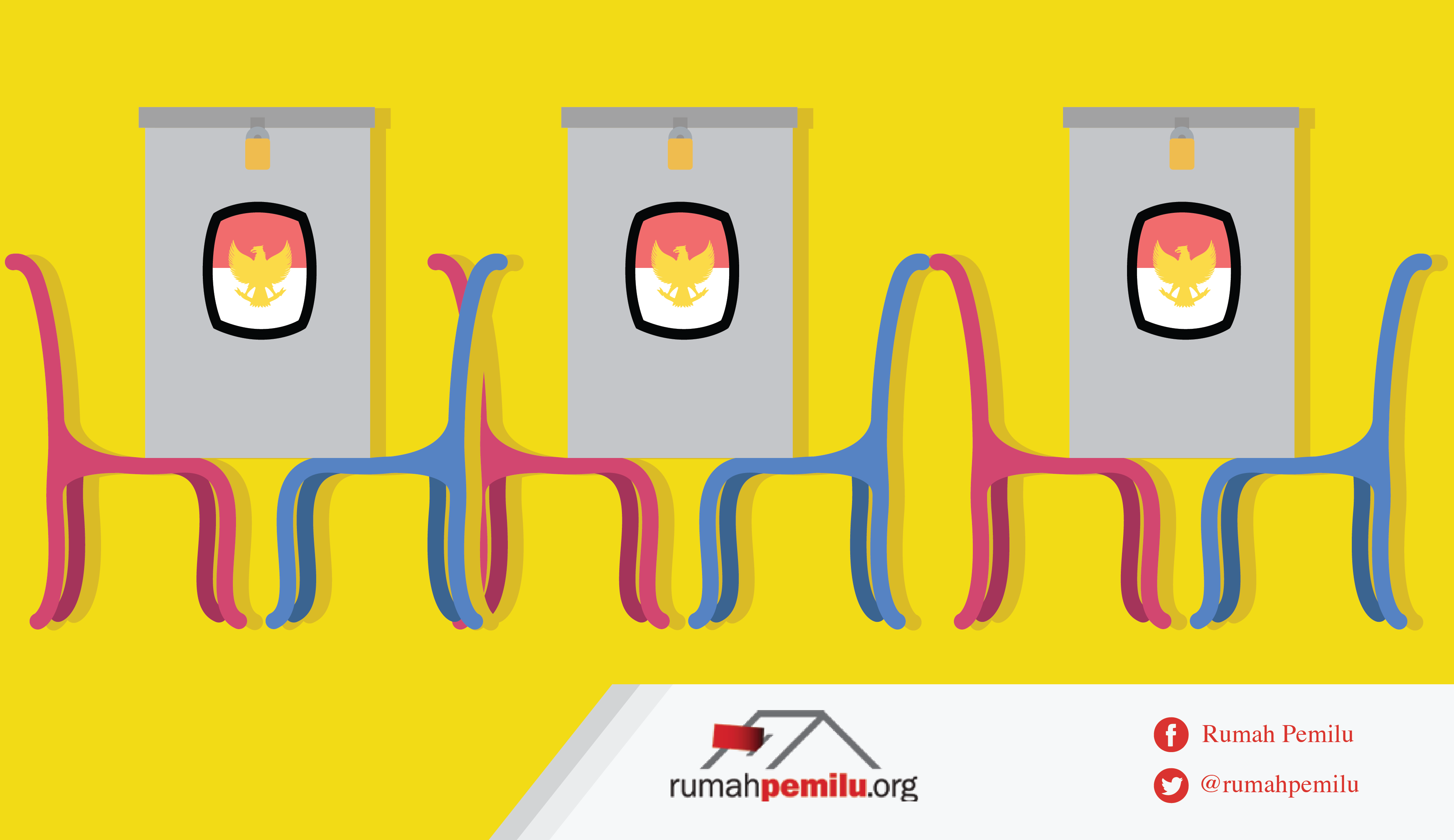Meski menuai banyak kritikan, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) tetap melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko. Kunjungan dilakukan pada 11-16 Maret 2017 dengan tujuan mempelajari sistem pemilu, pemungutan suara elektronik (e-voting), dan peradilan khusus pemilu (election trbunal). Kunjungan ini juga turut didampingi Tim dari Kementerian Dalam Negeri.
Jerman dipilih karena sistem pemilu Indonesia dianggap banyak mencontoh sistem yang berlaku di negara itu, selain juga untuk mempelajari keberlakuan e-voting. Sedang Meksiko jadi tujuan untuk mendalami e-voting dan dalam rangka mengelaborasi keberadaan Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atau TEPJF sebagai institusi peradilan Meksiko yang mengkhususkan diri dalam penegakan hukum pemilu dan berfungsi menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pemilihan federal serta menyatakan keabsahan hasil pemilu.
Tak tanggung-tanggung, anggota Pansus yang berjumlah 30 orang semuanya berangkat dengan dibagi jadi dua tim. 15 orang dipimpin Ketua Pansus Lukman Edy mengunjungi Jerman dan 15 orang lainnya mengunjungi Meksiko dipimpin Wakil Ketua Pansus Benny K. Harman.
Kunjungan kontroversial karena sejumlah alasan. Pertama, dilakukan di tengah sempitnya waktu untuk menyelesikan RUU Pemilu. Pansus bersama Pemerintah menargetkan RUU Pemilu disahkan paling lambat 28 April 2017. Ini bukan perkara mudah sebab RUU Pemilu merupakan penggabungan tiga substansi undang-undang dalam satu naskah (UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilu Legislatif, dan UU Pemilu Presiden). RUU ini meliputi 543 pasal yang terbagi dalam 6 buku. Pengalaman Pemilu 2014 saja, DPR dan Pemerintah memerlukan hampir 2 tahun untuk menuntaskan satu UU Pemilu Legislatif. Sementara RUU Pemilu ini baru mulai efektif dibahas November 2016.
Kedua, momentum studi banding dianggap tidak tepat sebab dilakukan ssaat pembahasan RUU Pemilu sudah masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM adalah respon resmi fraksi-fraks atas substansi RUU Pemilu yang diajukan Pemerintah. Melalui DIM ini, fraksi menyampaikan posisinya terhadap setiap pasal yang usulan Pemerintah. Menjadi aneh, ketika sikap fraksi sudah sangat jelas tercermin dalam DIM yang sedang dibahas, Pansus yang anggotanya notabene mewakili fraksi baru memutuskan untuk studi banding.
Mestinya, jika DPR memerlukan penguatan wawasan keilmuan pemilu, studi banding ini dilakukan saat Pemerintah sedang menyusun naskah RUU Pemilu. Sehingga saat RUU Pemilu dikirim ke DPR mereka sudah siap dengan amunisi yang dirumuskan dalam DIM fraksi-fraksi.
Ketiga, studi banding dianggap tidak efektif dan efisien bahkan merupakan pemborosan karena memberangkatkan rombongan sangat besar di tengah keterbatasan waktu yang dimiliki untuk menyelesikan RUU Pemilu. Mestinya Pansus cukup mengoptimalkan keberadaan para tenaga ahli dan Badan Keahlian DPR untuk melakukan kajian dan studi komparasi terkait hal-hal yang ingin diketahui. Bahkan untuk efektifitas, Pansus cukup mengundang pakar dan praktisi dari dua negara tersebut datang ke Indonesia untuk berdialog. Atau untuk lebih efisien melakukan diskusi via teleconference di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan metode ini, tidak hanya Pansus yang mendapat manfaat, masyarakat luas pun bisa dapat pengetahuan tambahan jika forumnya terbuka dan dibuka untuk umum.
Keempat, studi banding dianggap tidak relevan karena Jerman dan Meksiko bukanlah negara yang tepat untuk memenuhi tujuan Pansus. Guru Besar Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti secara terbuka mempertanyakan relevansi studi banding ini. Sebab Jerman sebagai negara tujuan memberlakukan sistem pemilu berbeda dengan Indonesia. Jerman menerapkan sistem pemilu campuran atau Mixed Member Proportional (MMP) yang merupakan gabungan sistem mayoritarian dan sistem proporsional daftar tertutup, sedang Indonesia sejak 2009 menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak.
Sebaliknya, Syamsuddin Haris, Guru Besar Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut studi banding ini sekedar alasan Pansus untuk pelesiran ke luar negeri. Dugaan ini dinilai wajar banyak pihak, antara lain karena Jerman sebagai tujuan belajar e-voting sudah meninggalkan metode ini dan beralih ke pemilihan manual sejak tahun 2005, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) Jerman memutuskan bahwa mesin pemungutan suara elektronik yang mereka gunakan inskonstitusional karena bertentangan dengan prinsip universal transparansi pemilu.
Sayangnya, Pansus bergeming. Mereka menegasikan suara agar tidak berangkat ke luar negeri dan cukup mengoptmalkan pembahasan melalui diskusi dan minta masukan dari para akademisi, pakar, dan ahli dalam negeri. Pansus beralasan kunjungan ini tidak mengganggu jadwal penyelesaian RUU Pemilu. Sebab 17 Maret Pansus melalui Panitia Kerja (Panja) sudah bisa melanjutkan rapat-rapat dengan Pemerintah, karena 16 Maret mereka sudah kembali ke Jakarta. Nyatanya, berdasar pantauan Perludem, pada tanggal yang dijanjikan tersebut, sama sekali tidak ada pembahasan lanjutan RUU Pemilu oleh Panja dan Pemerintah.
Bahkan dalam suatu kesempatan Benny Kabur Harman beralasan studi banding ke luar negeri tetap diperlukan karena masukan pakar dalam negeri kurang memadai bahkan tidak bermutu. Pernyataan menyakitkan bagi lingkungan akademik Indonesia. Mengingat pola kerja Pansus yang praktiknya cenderung tidak fokus dan terarah dalam meminta masukan. Pernah dalam sebuah rapat dengar pendapat umum, dalam undangan dijadwalkan berlangsung pukul 10.00-16.00 WIB, namun mendadak diubah sepihak menjadi dua jam saja. Lantas masukan berkualitas macam apa yang bisa diperoleh dalam waktu hanya 2 jam?
Nasi sudah jadi bubur, sekuat apapun publik menahan, studi banding tetap terlaksa. Lalu, apa yang bisa dilakukan saat ini? Sudah pasti publik wajib menagih Pansus agar menepati janji dan target kinerja yang sudah dibuat. RUU Pemilu tidak boleh molor. Jika RUU Pemilu terlambat disahkan maka kredibilitas DPR taruhannya. Sebab Pansus berkali-kali mengatakan studi banding tidak berpengaruh pada penyelesaiann RUU Pemilu.
Pansus Pemilu harus buktikan mereka mampu penuhi janji. Demi nama baik anggotanya dan marwah DPR yang kian terpuruk akibat berbagai peristiwa yang menimpanya. Cukuplah DPR dinilai sebagai lembaga paling korup oleh responden dalam survei yang digelar Global Corruption Barometer (GBC) 2017. Jangan ditambah lagi dengan gelar lain akibat Pansus Pemilu ingkar janji dengan sesumbar yang sudah dibuatnya sendiri. Itu pun kalau kredibilitas masih mereka anggap penting.
Karena keterbatasan waktu yang ada, Pansus harus bekerja strategis sesuai prioritas. Dalam waktu kurang dari 6 pekan tak mungkin melakukan perubahan fundamental atas sistem pemilu Indonesia. Apalagi tahapan Pemilu Serentak 2019 ditargetkan mulai 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya, Juni 2017 tahapan Pemilu 2019 sudah dilaksanakan.
Untuk itu, sebaiknya Pansus fokus pada tiga hal saja. Pertama, memastikan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan sebagai konsekwensi logis penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden secara serentak. Kedua, membuat pengaturan tindak lanjut berbagai Putusan MK yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam penerapannya. Ketiga, memperkuat aspek keadilan pemilu (electoral justice) yang selama ini jadi ketimpangan luar biasa dalam mewujudkan pemilu jurdil dan demokratis. Khususnya yang berkaitan upaya memerangi politik transaksional, politik uang, dan manipulasi suara dalam pemilu.
Dan keempat, DPR bersama Pemerintah jangan melompat terlalu jauh dengan membuat aturan baru untuk menambah jumlah kursi anggota DPR ataupun mengubah sistem pemilu, sebab dua hal itu tidak bisa diterapkan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat dan juga kesiapan struktur dan infrastruktur. Jika hal itu dilakukan, alih-alih menghasilkan RUU Pemilu yang demokratis, bisa jadi DPR akan menuai kecaman, krtitik, dan rasa kecewa publik.
RUU Pemilu mestinya jadi modal hulu untuk membenahi pemilu. Ia bisa jadi perangkat efektif untuk meningkatkan mutu demokrasi Indonesia. Namun, jika regulasi sekedar jadi alat untuk mengokohkan kekuasaan dan menjauhkannya dari aspirasi orang banyak, maka jangan pernah berharap keadilan pemilu akan terwujud. Na’udzubillah. []
Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal