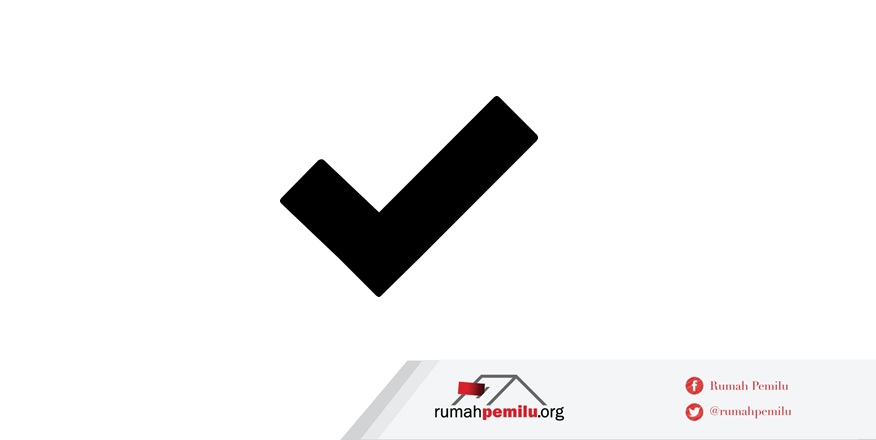Pemilu perlu dirumuskan melalui undang-undang untuk meminimalkan peran negara. Ada tren keliru dari perubahan regulasi. Selama ini pemangku kepentingan pemilu menganggap, untuk membuat pemilu semakin baik aturan harus diperbanyak. Konsekuensinya peran negara semakin bertambah. Hasilnya, seperti yang terjadi di bidang lain, negara tak hanya makin otoritarian tapi juga merengut kebebasan.
Salah satu bentuk intervensi terlalu jauh negara terhadap pemilu adalah dengan menetapkan syarat partai politik peserta pemilu berdasarkan kepemilikan kantor. Negara merengut kebebasan berpolitik ini tak hanya melalui undang-undang pemilu tapi juga undang-undang partai politik. Syarat berdirinya partai politik salah satunya adalah harus memiliki kantor di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. Syarat berdiri partai politik ini di-copypaste menjadi salah satu syarat kepesertaan pemilu.
Dampak dari persyaratan itu membuat pemilu menjadi mahal. Partisipasi kepesertaan lebih ditentukan oleh kepemilikan uang. Partai politik butuh uang amat banyak untuk mendirikan dan menjalankan kesekretariatan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. “Rakyat” dalam redaksi “dari, oleh, dan untuk” berganti jadi “pemodal”.
Mahalnya kepesertaan pemilu tak hanya berlaku bagi partai politik secara lembaga tapi juga para calon anggota dewan. Konstitusi sudah menutup DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bagi perseorangan. Dengan mahalnya beban pembiayaan kantor, warga yang mau jadi dewan disyaratkan partai politik menyetorkan uang untuk ongkos politik. Bahkan dengan jual beli nomor urut calon: nomor piro wani piro? (NPWP).
Selain negara mengatur hal yang tak perlu diatur di pemilu legislatif, negara pun mengatur hal yang tak perlu diatur di pemilu eksekutif. Menjadi calon presiden hanya bisa melalui jalur partai politik atau koalisinya dengan kepemilikan 20% kursi DPR. Malah berdasarkan rancangan undang-undang pemilu per 11 Juni 2017, syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang sebelumnya 35 tahun menjadi 40 tahun.
Salah kaprah kesetaraan
Setelah negara membatasi kebebasan pencalonan berdalih memperbaiki kualitas calon, negara pun membatasi kebebasan partisipasi dukungan dengan batasan sumbangan. Dalihnya adalah untuk menciptakan kesetaraan kontestasi. Jika jumlah sumbangan dibebaskan, maka pemilu hanya mengkampanyekan dan memenangkan peserta yang paling banyak mendapat sumbangan.
Dalih itu merupakan salah kaprah dari kesetaraan. Pembatasan sumbangan tetap menghadirkan ketimpangan kontestasi malah pasti memberangus kebebasan. Semangat kebebasan utuh melarang regulasi yang berpandangan membedakan kelas ekonomi. Menjadi diskriminatif bila negara berpikir, warga kaya cenderung menggunakan kekuatan finansial untuk kepentingan jahatnya sedangkan warga miskin tak akan jahat karena tak bisa menggunakan kekayaannya.
Prinsip free and fair pemilu jadi tak konsisten jika regulasinya menduga, kelas atas cenderung jahat karena bisa memberi uang sangat banyak dengan mengabaikan kepentingan publik. Kebebasan utuh mesti berprasangka baik bahwa kelas atas berkebutuhan menyumbang berdasar kemampuan sama halnya kelas ekonomi bawah yang juga ingin menyumbang berdasar kemampuan.
Intervensi pembatasan dana kampanye selama ini menghasilkan keterbukaan pura-pura dalam pemilu. Ada pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu tapi jumlah belanja kampanye di atas kertas jauh dari realitas. Banyak reklame kampanye yang menyesakan ruang publik, politik uang marak, atribut dan t-shirt berserak, tapi jumlah belanja kampanye dalam laporan malah lebih murah dari harga rombongan mobil yang digunakan tim sukses saat melaporkan dana kampanye.
Terlepas dari sebutan “pesta demokrasi”, pemilu pada dasarnya membutuhkan pendanaan sangat banyak. Kampanye menjadi salah satu bentuk aktivitas pemilu yang tinggi kebutuhan uang. Semua karena pemilihan pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat” berusaha meyakinkan dan melibatkan semua rakyat sebagai pemilih.
Karena prinsip dan bentuk itu, pesta demokrasi bertantangan bagaimana bisa menjadi ruang bebas kontestasi dan partisipasi yang tak diskriminatif. Atas nama rakyat, pemilu tentu saja harus bisa mengakomodir bentuk-bentuk pendana kelas ekonomi bawah. Atas nama rakyat pun, pemilu tak boleh membatasi besaran sumbangan kelas ekonomi atas.
Sedikit/banyak-nya uang diposisikan setera dengan sedikit/banyak-nya massa, serta buruk/baik-nya kualitas personal dan program. Jika kualitas personal dan progam baik, maka dukungan massa dan uang cenderung banyak. Jika identitas/kepentingan massa banyak maka uang beserta kualitas dan program pun cenderung mendekat bersatu. Kesukarelaan mendukung dan membeli t-shirt, stiker, dan bendera PKS atau Jokowi adalah bukti.
Kita butuh pemilu minimal yang menempatkan kebebasan secara utuh. Tak perlu membatasi kepesertaan karena pembatasan selama ini membuat pemilu mahal yang diskriminatif dalam kontestasi dan capaian kekuasaan. Dari 73 partai politik yang terdata di Kementerian Hukum dan HAM, lebih dari 80%-nya tak bisa jadi peserta pemilu. Keadaan saat ini sangat menyedihkan karena ragam ideologi partai politik di Indonesia diganti satu ideologi: uang-isme.
Pemilu minimal pun tak perlu membatasi sumbangan kampanye. Belanja kampanye Partai Nasdem dan Partai Perindo paling banyak tapi kita yakin keduanya tak akan memenangkan pemilu. Prabowo Subianto sudah terlalu banyak dan panjang berkampanye tapi tak pernah memenangkan pemilu. Jika kualitas peserta pemilu baik, tren dukungan massa dan uang pun banyak. Jika identitas atau kepentingan massa banyak, maka uang beserta kualitas dan program pun cenderung mendekat bersatu. []
USEP HASAN SADIKIN
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal