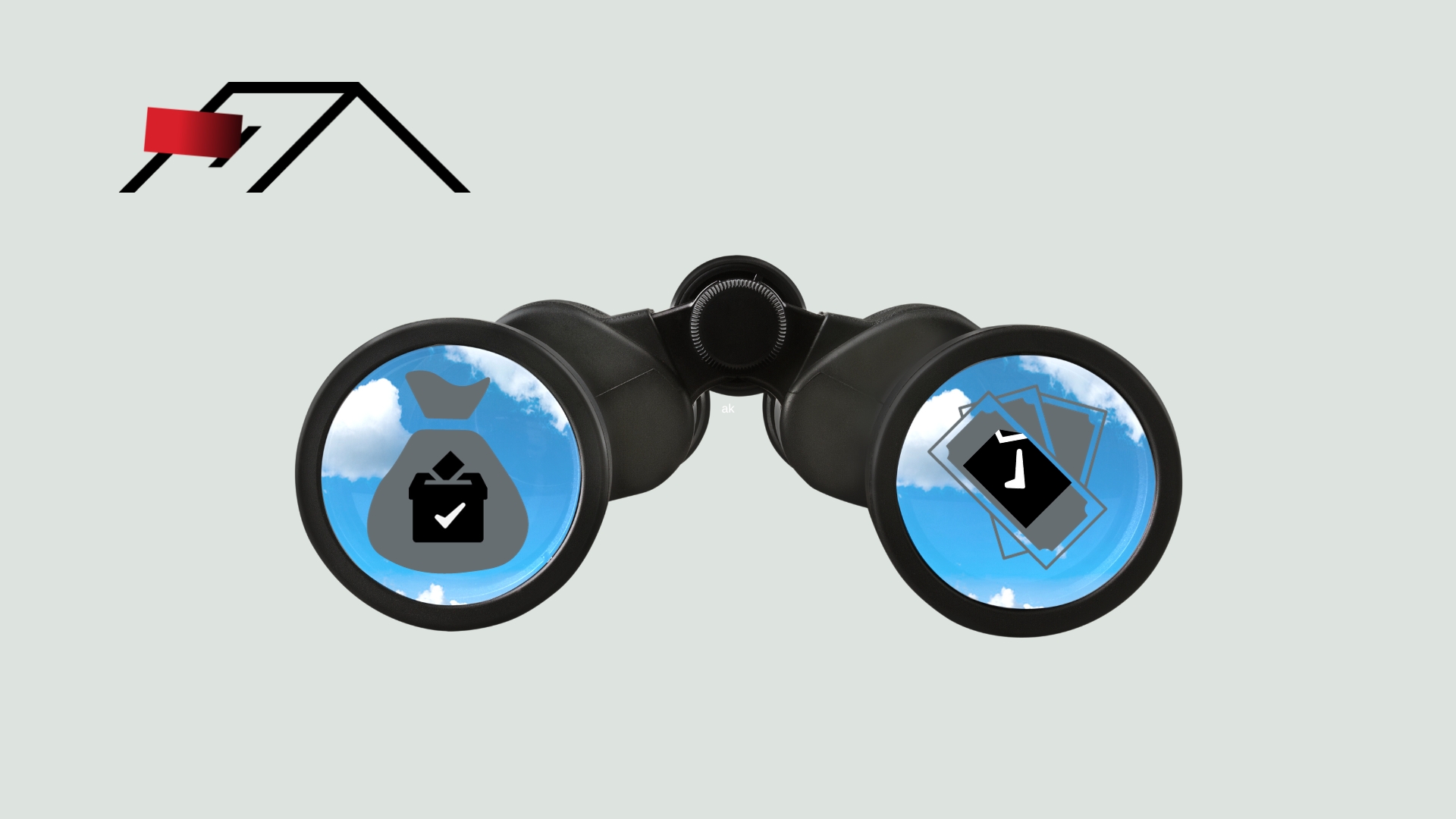Demokrasi Indonesia cacat, begitulah bunyi data dari studi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU). Indonesia hanya mendapatkan skor 6,71 (skala 10) pada indeks demokrasi tahun 2022. Nilai ini tak mengubah indeks demokrasi tahun sebelumnya dan masih memosisikan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang belum sempurna alias cacat.
Dengan skors 6,71, Indonesia hanya bertengger di posisi ke-54—turun dari tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-52—dari total 167 negara. Merujuk pada laman resmi EIU, terdapat lima kategori yang diperhitungkan dalam penilaian ini, yakni proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Pada kategori budaya politik, Indonesia hanya mendapatkan skor 4,38.
Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, yang mengakar sejak dulu. Tindakan amoral ini dilakukan oleh pelbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat negara. Tampaknya, penyakit ini telah merasuki dan menginfeksi aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengutip dari “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022” yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Februari 2023 kemarin, kasus korupsi di Indonesia meningkat 8,63% pada tahun 2022 dengan 579 kasus, dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 533 kasus. Jumlah tersangka korupsi juga meningkat menjadi 1.396 orang pada 2022, naik 19,01% dari 1.173 orang pada 2021. Dari data, bisa diketahui bahwa kasus korupsi di Indonesia meningkat, yang mana bisa juga membuat demokrasi Indonesia bobrok.
Faktor kebobrokan
Bobroknya indeks demokrasi Indonesia tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang juga berpengaruh terhadap demokrasi Indonesia adalah adanya korupsi politik. Korupsi politik menjadi salah satu elemen kunci yang memengaruhi penurunan kualitas demokrasi.
Fenomena ini bisa mengikis kekuatan dan efektivitas institusi pemerintahan, menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap praktik korupsi lebih lanjut dan berpotensi merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Korupsi pun memperberat masalah ketidaksetaraan dalam partisipasi politik karena dalam demokrasi yang ideal, setiap warga negara semestinya memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi.
Selain itu, korupsi politik juga merugikan pembangunan negara karena sering kali mengarah pada penyalahgunaan dana dan sumber daya publik, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Ini juga bisa menghasilkan kebijakan publik yang tak efektif dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam korupsi, bukan masyarakat secara keseluruhan.
Artidjo Alkostar menyatakan bahwa korupsi politik yang terjadi di Indonesia tercermin dalam sejumlah kasus korupsi yang secara nyata dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara negara. Maraknya korupsi politik yang terungkap di Indonesia mencerminkan sejauh mana korupsi politik telah merajalela, melibatkan pelbagai tingkatan kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif.
Praktik korupsi ini muncul ketika individu dalam posisi kekuasaan memperalat posisi mereka untuk memperkuat pengaruh, status, dan kekayaan pribadi. Regulasi dan hukum sering kali disalahgunakan, diabaikan, atau disesuaikan untuk melayani kepentingannya sendiri, sehingga memungkinkan mereka menghindari hukuman dan mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka.
Berita yang santer terdengar belakangan ini adalah mengenai korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, terkait Base Transceiver Station (BTS), dengan dakwaan merugikan negara sebesar Rp8 triliun. Peristiwa ini tentu melecehkan bangsa dan negara, serta berdampak buruk bagi budaya politik Indonesia.
Sebelumnya, pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sudah ada empat menteri yang ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan korupsi. Adanya dakwaan korupsi terhadap Menkominfo tentu bisa menambah noktah hitam dalam pusaran pemerintahan Indonesia, khususnya terkait dengan kasus korupsi, yang tentu berimplikasi buruk pada kualitas demokrasi.
Ongkos politik tinggi
Tingginya ongkos politik merupakan salah satu faktor yang membuat timbulnya korupsi. Hal ini juga diaminkan oleh ICW, yang mana salah satu motif pejabat terjerumus dalam praktik korupsi adalah ongkos politik yang mahal. Kemudian, sejumlah data juga menunjukkan bahwa ongkos politik di Indonesia sangat mahal.
Menurut data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ongkos politik calon wali kota atau bupati rata-rata mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Sementara, gubernur dan wakilnya membutuhkan ongkos sebesar Rp 100 miliar. Kemudian, ongkos politik yang mesti dikeluarkan bagi setiap calon presiden dan wakilnya di Indonesia setidaknya mesti menyiapkan modal minimal Rp 5-7 triliun.
Hal ini disebabkan karena dalam proses kampanye juga ditemukan korupsi politik, seperti jual-beli suara, pembiayaan kampanye, dan sebagainya. Hal ini tentu tidak gratis, para calon nakhoda bangsa Indonesia mesti merogoh kocek lebih dalam untuk bisa duduk di kursi-kursi kepemimpinan politik.
Mahalnya ongkos politik di Indonesia membuat para pejabat negara bisa terjerumus ke dalam jurang korupsi, mereka berpikir untuk mengembalikan modal besar yang telah dikeluarkan ketika kampanye. Mau tidak mau, suka tidak suka, ongkos politik merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.
Bobroknya Penegakan Hukum
Untuk memperbaiki situasi demokrasi, perlu adanya penegakan hukum yang kuat dalam menangani korupsi politik serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi untuk memastikan nilai-nilai demokrasi dihormati dan dijalankan. Akan tetapi, pada realitasnya, penegakan hukum di Indonesia juga bobrok.
Para penegak hukum yang kurang berkualitas menjadi salah satu penyebab bobroknya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi, salah satunya adalah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deretan kebobrokan KPK bisa ditemui pada pelbagai pemberitaan di media massa, termasuk pemecatan puluhan pegawai KPK—yang kemudian dikenal sebagai IM57+ (Indonesia Memanggil)—yang punya integritas pada 2021 kemarin.
Banyaknya kasus mengenai pelanggaran kode etik oleh para petinggi KPK juga merupakan bukti bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Tidak adanya tindakan tegas menjadi salah satu penghambat penegakan hukum di Indonesia, pimpinan KPK yang terbukti melanggar kode etik hanya dijatuhi sanksi ringan. Tentu kebobrokan ini berimplikasi buruk bagi pemberantasan korupsi politik di Indonesia.
Kualitas penegakan hukum yang bobrok juga bisa dipengaruhi oleh masalah sistem hukum yang juga bobrok, seperti kurangnya transparansi, mekanisme penegakan hukum yang lemah, serta pengaruh politik dan kekuasaan. Di sisi lain, upaya media dan masyarakat sipil dalam mengungkap kasus korupsi sering kali dihambat oleh peraturan yang banyak terdapat pasal karet bernama UU ITE, hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers dan perlindungan bagi whistleblower belum terjamin sepenuhnya.
Maraknya kasus korupsi politik ditambah dengan bobroknya penegakan hukum menegaskan bahwa perlu adanya reformasi hukum dan struktural yang lebih luas untuk menangani korupsi di Indonesia, mencakup perbaikan sistem pengadilan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan hukum dan regulasi antikorupsi. []
RAIHAN MUHAMMAD
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
 Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal